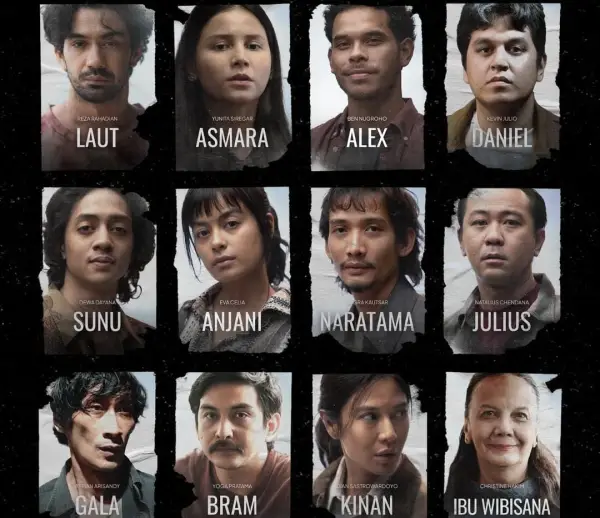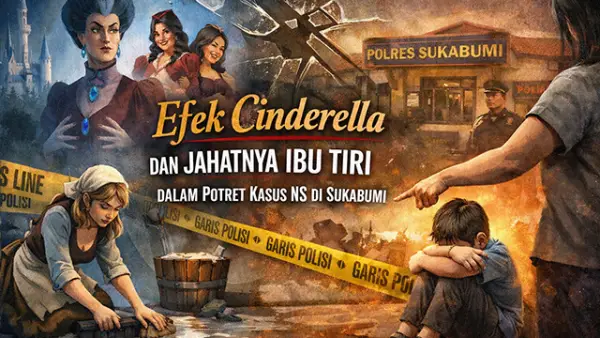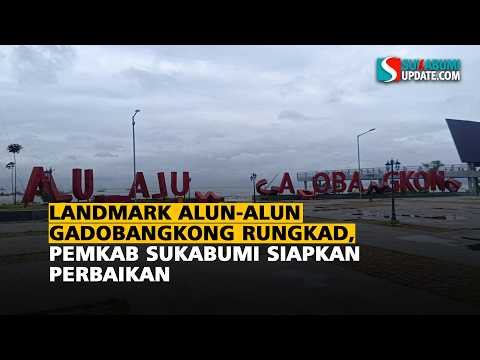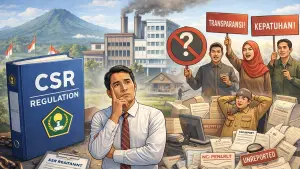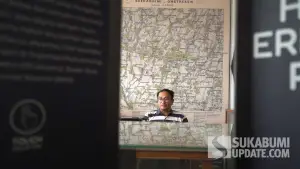SUKABUMIUPDATE.com – Malam dingin menyelimuti Kasepuhan Ciptamulya, Kampung Ciptamulya, Desa Sirnaresmi, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Dua pria paruh baya melangkah santai di jalan setapak yang masih basah usai diguyur hujan sore. Di tengah gulita, hanya cahaya senter di tangan mereka yang menjadi penuntun.
Mereka adalah Opok (44) dan Uday (55), dua warga yang dipercaya sebagai Manintin di Kampung Adat tersebut. Malam itu, perintah dari Ketua Adat Kasepuhan Ciptamulya, Abah E. Suhendri Wijaya, membuat keduanya bergerak cepat. Air yang biasanya mengalir deras ke perkampungan mendadak terhenti sejak petang.
Langkah keduanya terhenti ketika melihat pipa ukuran sekitar 4 inci yang menyalurkan air ke kampung tertimpa longsoran tanggul di salah satu petak sawah. Tekanan tanah membuat paralon itu retak hingga aliran air tersumbat. Tanpa banyak bicara, mereka segera bekerja. Dengan peralatan sederhana dan pipa cadangan yang selalu dibawa, bagian yang rusak dipotong lalu diganti. Tak lama kemudian, aliran air kembali lancar menuju sawah dan rumah-rumah penduduk.
Tugas Manintin memang tidak ringan: memastikan aliran air dari sumber tetap terjaga, merawat instalasi, sekaligus membagi distribusi secara adil untuk kebutuhan sehari-hari warga maupun lahan pertanian. Sumber utama air ini berasal dari Sungai Cipanengah, sekitar 3 kilometer dari perkampungan, menembus hutan di lereng Gunung Halimun.
Baca Juga: Bayu Permana Bicara Tradisi Kasepuhan dan Patanjala: Sumber Nilai Pelestarian Alam Sukabumi
Pipanisasi dan Ketahanan Air Warga Adat
Sungai tersebut memiliki empat sirah cai atau mata air: satu aliran di Pasir Dungkil, dua aliran di Nyampiong, dan satu aliran lagi di Lembah Neundeud. Dari sumber itu, air tidak hanya mengairi lahan pertanian, tetapi juga disalurkan ke puluhan rumah warga di 2 dusun (Ciptamulya dan Cibongbong) serta 2 WC umum di Kasepuhan Ciptamulya. Alirannya mengalir melalui jaringan pipa sederhana yang menuruni lereng perbukitan dan melintas di area persawahan terasering, sebelum akhirnya ditampung terlebih dahulu di sejumlah bak penampungan atau tandon.
 Warga menunjukkan salah satu sirah cai atau mata air yang mengalir ke perkampungan maupun sawah di Kasepuhan Ciptamulya.
Warga menunjukkan salah satu sirah cai atau mata air yang mengalir ke perkampungan maupun sawah di Kasepuhan Ciptamulya.
Dua di antaranya berada di belakang Imah Gede, rumah tinggal sekaligus balai pertemuan milik Ketua Adat. Kedua bak beton yang terlihat berlumut dengan ukuran bervariasi di lokasi tersebut berfungsi sebagai tempat penyaringan sekaligus pusat distribusi air. Dari bak inilah air dialirkan ke rumah warga untuk keperluan mandi hingga mencuci melalui sejumlah pipa dan selang berwarna putih, biru, dan hijau. Tanpa pompa, air mengucur deras ke dalam bak, menimbulkan riak dan bunyi gemericik yang terus-menerus terdengar di sekitar Imah Gede.
“Setiap bak untuk satu dusun. Suplai air dari bak di Imah Gede yang paling jauh sampai ke (dusun) Cibongbong, pakai selang panjangnya sekitar 100 meter,” jelas Opok saat ditemui sukabumiupdate.com di rumah panggungnya yang beratapkan ijuk dan terletak sekitar 100 meter dari Imah Gede, Selasa (30/9/2025).
Opok menyampaikan, dampak musim kemarau biasanya terasa ketika debit air di bak penampungan berkurang, sehingga alirannya ke rumah penduduk tidak lagi sederas hari-hari biasa. Kondisi itu membuat warga harus lebih bijak dalam penggunaan air. Sebaliknya, saat musim hujan, debit air justru melimpah karena selain dari sirah cai, bak tersebut juga ikut menampung air hujan yang turun langsung ke permukaan.
"Tahun ini belum pernah kami kekeringan atau kemarau panjang. Tapi memang sempat beberapa tahun lalu sampai 5 bulan kemaraunya, namun hasil sawah atau kebun tetap ada, belum pernah gagal panen atau paceklik. Mata air tetap mengalir ke sungai-sungai kecil ke sawah meskipun debitnya kecil," jelasnya.
 Bak atau tandon air yang berada di belakang Kasepuhan Ciptamulya.
Bak atau tandon air yang berada di belakang Kasepuhan Ciptamulya.
Musim yang Bergeser dan Peringatan BMKG
Sementara itu menurut Prakiraan BMKG, wilayah Kecamatan Cisolok dan sekitarnya kini mengalami pergeseran pola musim yang cukup signifikan. Awal musim hujan dan kemarau tidak lagi stabil seperti dua dekade lalu. Patria Wirayudha, forecaster iklim BMKG, menjelaskan bahwa perubahan pola cuaca ini menyebabkan distribusi curah hujan menjadi tidak merata.
"Pergeseran ini bisa berupa masuknya awal musim kemarau yang lebih lambat atau lebih cepat, awal musim hujan yang lebih terlambat, atau durasi musim kemarau atau hujan yang pendek atau panjang," ungkapnya.
Untuk tahun 2025, Patria menyebut wilayah Sukabumi, termasuk Cisolok, diprakirakan mengalami musim hujan hampir sepanjang tahun dengan puncak pada Oktober hingga November. Kondisi ini berpotensi menimbulkan cuaca ekstrem, baik berupa hujan lebat disertai angin kencang maupun periode kering yang lebih panjang di bulan-bulan tertentu.
"Diprakirakan terjadinya puncak musim hujan akan ada yang jatuh pada bulan Oktober. Untuk sebagian wilayah Sukabumi dan akan ada yang jatuh bulan November. Sifat musim hujan untuk tahun ini adalah normal untuk sebagian kecil wilayah Sukabumi dan wilayah lainnya adalah atas normal," jelasnya.
Baca Juga: Pemkab Sukabumi Ajukan 4 Tradisi Kasepuhan Jadi Warisan Budaya Tak Benda
BMKG kemudian mendorong konservasi untuk ketahanan ekosistem sebagai salah satu fokus adaptasi perubahan iklim bagi masyarakat adat di Cisolok. Utamanya, dengan melaksanakan reboisasi atau penghijauan dengan spesies asli yang tahan kondisi ekstrem; pohon berakar kuat agar mencegah erosi dan longsor.
"Melindungi hutan adat atau kawasan konservasi lokal sebagai buffer terhadap cuaca ekstrem. misalnya sebagai pelindung dari angin, banjir, pengaturan
aliran air tanah," ujar Patria.
Patria mengatakan, BMKG juga mendorong perbaikan atau pembangunan irigasi sederhana di daerah pertanian adat agar air bisa dialirkan ke kebun atau tanaman saat kekeringan atau memperlambat aliran saat hujan deras.
Keterangan BMKG ini memperkuat pengamatan warga adat Ciptamulya, bahwa perubahan musim kini kian sulit diprediksi. Meski demikian, mereka masih mampu menjaga ketahanan pangan dan sumber air dengan memadukan pengetahuan lokal dan gotong royong sebagai bentuk adaptasi terhadap perubahan iklim.
Leuit dan Siklus Panen Sekali Setahun
Ketersediaan air yang tetap terjaga, disokong sistem manajemen leuit alias lumbung padi, membuat Kasepuhan Ciptamulya tak pernah mengalami krisis pangan. Penduduknya juga tak pernah mengalami gagal panen lantaran hama atau kekurangan air, sepanjang mereka mampu mengingat. Di tengah perubahan iklim, bencana longsor menjadi ancaman, bukan banjir. Hal itu karena tidak ada sungai besar yang membelah perkampungan tersebut.
 Leuit Si Jimat Kasepuhan Ciptamulya.
Leuit Si Jimat Kasepuhan Ciptamulya.
Kasepuhan Ciptamulya merupakan bagian dari Kesatuan Adat Banten Kidul (SABAKI). Komunitas desa adat sunda ini menjadi salah satu dari beberapa kasepuhan yang berada di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS). Selain Ciptamulya, terdapat pula Kasepuhan Sinar Resmi dan Kasepuhan Gelaralam (Ciptagelar) yang lokasinya secara administratif berada di wilayah Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi.
Sebagian besar warga kampung adat Ciptamulya merupakan masyarakat petani, bekerja sebagai petani dan buruh tani di sawah atau di ladang atau yang disebut “huma”, di antaranya ada juga yang mempunyai pekerjaan sampingan seperti pengrajin, penyadap nira, pengukir bedog (golok), dan pandai besi. Kondisi ini menempatkan tanah merupakan bagian yang penting. Tanah bukan hanya sebagai tempat memproduksi bahan pangan, tetapi juga menjadi dasar kehidupan sosial.
Adapun jenis sawah yang dikelola sebagian besar merupakan sawah tadah hujan. Hal ini juga disebabkan oleh kondisi topografi perkampungan ini yang berada pada ketinggian antara 1.000 hingga 1.200 meter di atas permukaan laut, dengan kontur berbukit-bukit. Oleh karena itu sistem pipanisasi menjadi tulang punggung para petani di kasepuhan tersebut yang di bulan Oktober ini sudah masa penyemaian lahan sawah pasca Serentaun yang digelar Juli 2025 lalu.
 Kondisi sawah tadah hujan di Kasepuhan Ciptamulya.
Kondisi sawah tadah hujan di Kasepuhan Ciptamulya.
Petani di Kasepuhan Ciptamulya berbeda dengan daerah lainnya dengan hanya melakukan penanaman padi satu tahun sekali sesuai peraturan adat yang berlaku di komunitas. Hasil panen disimpan dalam leuit. Tak heran saat memasuki desa ini leuit-leuit berjejeran apik memenuhi desa. Satu keluarga kecil minimal harus punya satu leuit. Ada pula leuit komunal bernama leuit Si Jimat untuk kepentingan bersama yang letaknya berada di pinggir imah gede.
Dalam setahun masyarakat kasepuhan hanya mempunyai siklus panen sekali. Pola pertanian demikian berangkat dari pandangan tradisional bahwa tanah diasosiasikan
sebagai ibu yang dihargai; yang hanya dapat melahirkan sekali dalam setahun.
Selain bertanam padi, pada saat musim kemarau para petani memanfaatkan ladang untuk bertanam berbagai jenis sayuran, palawija atau ikan untuk lahan sawah yang diberakan.
Bagi masyarakat adat, hutan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan. Di Kasepuhan Ciptamulya, hutan dibagi menjadi tiga kategori utama: hutan titipan, hutan tutupan, dan hutan garapan. Hutan titipan dipandang sebagai kawasan sakral yang sama sekali tidak boleh dimasuki atau diganggu. Hutan tutupan boleh dimanfaatkan secara terbatas dengan seizin pemangku adat, biasanya untuk keperluan membangun rumah. Adapun hutan garapan atau produksi menjadi ruang hidup masyarakat sehari-hari, yang dimanfaatkan sebagai sawah, ladang, dan kebun.
Ancaman Tambang Ilegal
Kini di tengah ancaman perubahan iklim, kerusakan hutan akibat praktik penambangan emas tanpa izin (PETI) di kawasan hutan garapan menjadi tantangan nyata bagi Kasepuhan Ciptamulya. Kondisi tersebut tidak hanya mengancam kelestarian lingkungan, tetapi juga keberlangsungan budaya masyarakat adat.
Hal itu diakui langsung oleh Ketua Adat Kasepuhan Ciptamulya, Abah E. Suhendri Wijaya (52) atau akrab disapa Abah Hendrik. Ia menyebut perubahan besar memang terasa dalam dua dekade terakhir.
“Dua puluh tahun ke belakang, hutan masih benar-benar asri. Banyak kayu, tidak terlalu gundul, jalan tani pun tidak bisa dilewati motor. Tapi sekarang, setelah ada jalan yang diperbaiki sampai ke pegunungan, orang bisa bawa dolken, motor yang mengambil kayu dari hutan. Memang kebanyakan dilakukan warga, bukan berarti maling, tapi dampaknya ada kayu yang keluar dari taman nasional maupun talun,” ungkap Abah Hendrik.
Meski begitu, ia menyebut cuaca di Kasepuhan Ciptamulya sejak dirinya memimpin pada 2011 tergolong lebih stabil. Namun ia khawatir, jika kemarau panjang tiba-tiba disusul hujan deras secara terus-menerus, potensi bencana longsor akan meningkat.
Menurutnya, kerusakan terbesar justru datang dari maraknya penambangan emas ilegal. Aktivitas tersebut tidak hanya merusak lahan, tetapi juga perlahan mengikis budaya gotong royong warga, karena sebagian kecil masyarakat ikut terlibat dalam kegiatan pengolahan hasil tambang.
“Sekarang hancurnya lahan karena banyak penambangan ilegal. Itu terasa sekali. Kegiatan gotong royong atau untuk tani jadi berkurang karena orang sibuk ke tambang. Biasanya liburnya hari Jumat atau hari-hari tertentu. Rata-rata yang menambang itu pemuda, bahkan banyak yang sudah berkeluarga,” jelasnya.
Ia mengakui, upaya melarang aktivitas tambang bukan hal yang mudah.
“Kalau untuk melarang bingung juga. Serba salah. Kasepuhan dan kepala desa juga tidak bisa melarang seutuhnya. Sedangkan kalau dibiarkan, ke depan dampaknya (hutan) bisa gundul, bisa longsor. Lokasinya di hutan taman nasional, hutan garapan,” ujarnya.
 Penampakan tambang emas di Gunung Enggang.
Penampakan tambang emas di Gunung Enggang.
Karena itu, Abah Hendrik menilai perlu adanya dukungan hukum tertulis dari pemerintah daerah agar masyarakat adat memiliki payung hukum yang kuat dalam melindungi dan mengelola hutan. Menurutnya, pengakuan wilayah masyarakat adat sebaiknya dituangkan dalam bentuk peraturan daerah (Perda), bukan hanya sebatas surat keputusan (SK).
“Kalau ada Perda, nantinya bukan oleh TNGHS atau polisi, tapi kasepuhan yang bisa langsung menggerakkan program-program penanaman dan penghijauan,” tegasnya.
Seperti dilaporkan oleh Odih Kustiandi, jurnalis masyarakat adat Nusantara (AMAN), tanah yang selama ini digarap warga Ciptamulya adalah tanah adat. Status tersebut berubah sejak pemerintah menetapkan kawasan itu sebagai bagian dari Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) pada 2004. Saat itu, terbit SK Menteri Kehutanan tentang pengalihan fungsi lahan dari Perum Perhutani menjadi kawasan taman nasional. Kondisi ini membuat masyarakat adat semakin sulit mengontrol ancaman kerusakan hutan di wilayah garapan yang telah dititipkan leluhur mereka sejak sebelum Indonesia merdeka.
Pantauan sukabumiupdate.com saat menelusuri jalur menuju sumber mata air sekitar 500 meter dari perkampungan menunjukkan pemandangan yang kontras. Dari kejauhan tampak jelas area tambang di salah satu lereng bukit yang dulunya hijau kini terkelupas, meninggalkan warna tanah cokelat terbuka. Di punggung bukit bernama Gunung Engang itu berdiri sekitar lima gubuk beratap terpal biru, berjejer mengikuti jalur tanah yang merayap menurun. Lanskap tersebut memperlihatkan perbedaan mencolok antara sisi hutan yang masih rimbun dan sisi bukit yang mulai terkoyak oleh aktivitas tambang.
Selain mengandalkan leuit atau lumbung padi sebagai sumber ketahanan pangan, Kepala Desa Sirnaresmi, Jaro Iwan Suwandri, mengatakan bahwa pemerintah desa juga berupaya mencegah bencana longsor melalui kegiatan penanaman pohon di sekitar mata air. Namun, ia mengakui kesulitan untuk melarang warga yang menebang pohon secara sembarangan atau ikut tambang karena faktor ekonomi.
“Masyarakat kan dicaram mah dicaram, tapi ngaleyeud mah ngaleyeud. Warga tidak tahu apakah area itu rawan atau tidak, karena tadi itu, faktor kebutuhan. Kalau kita melarang tapi pemerintah desa tidak bisa memenuhi kebutuhan mereka, ya akhirnya ke situ juga arahnya,” ungkap Jaro Iwan.
Ia memastikan pihaknya rutin melakukan sosialisasi agar warga tetap menjaga kelestarian hutan, serta menjalin koordinasi dengan pihak TNGHS.
“Kolaborasi dengan taman nasional untuk menjaga hutan sudah berjalan. Di sini kami punya prinsip, ‘leuweung hejo, urang masyarakat bisa ngejo’. Kemudian untuk mencukupi kebutuhan masyarakat dan mengantisipasi dampak perubahan iklim, desa punya program Katapang (Ketahanan Pangan). Kami salurkan sesuai kebutuhan warga Ciptamulya, misalnya untuk sarana air bersih atau irigasi ke area persawahan,” pungkasnya.
 Lokasi tambang berada di kawasan hutan garapan.
Lokasi tambang berada di kawasan hutan garapan.
Pemda Dorong Pipanisasi dan Pertanian Lestari
Pemerintah daerah melalui Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi turut menyoroti potensi pertanian berkelanjutan di wilayah adat seperti Ciptamulya. Menurut Eris Firmansyah, Kabid Penyuluhan dan Pengembangan Usaha Pertanian, pemerintah daerah memiliki program pendampingan khusus bagi petani adat di kawasan TNGHS berupa penyuluhan pertanian dan pembinaan kelompok tani.
“Kampung adat berada di hulu sungai dan wilayah tangkapan air, sehingga pembangunan pipanisasi merupakan langkah yang sesuai tanpa mengubah bentang alam. Kami telah membangun pipanisasi di Kasepuhan Ciptamulya dan Gelar Alam (Ciptagelar),” jelasnya.
Ia menambahkan, kolaborasi antara Dinas Pertanian dan Balai TNGHS terus dijalankan untuk melindungi lahan pertanian dari dampak tambang ilegal. “Kami membina budidaya pertanian lestari agar masyarakat turut menjaga kelestarian ekosistem,” ujarnya.
Sebagai langkah antisipasi, Dinas Pertanian telah menyiapkan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) agar lahan pertanian tidak dialihfungsikan, serta menggelar penyuluhan ramah lingkungan agar petani tetap menjaga sumber air alami di tengah ancaman krisis iklim.
Kasepuhan Ciptamulya kini berada di persimpangan antara mempertahankan harmoni dengan alam dan menghadapi tekanan ekonomi serta iklim yang kian tak menentu. Namun selama air masih mengalir dari sirah cai, dan leuit tetap penuh oleh padi hasil kerja bersama, harapan itu tetap hidup di kaki Gunung Halimun.