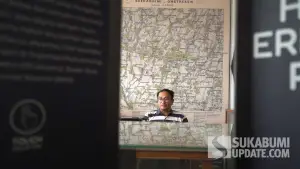Oleh : Hamidah, Praktisi Pendidikan
Setelah bertahun-tahun tertunda, akhirnya nama Soeharto kembali muncul di antara deretan tokoh yang diberi gelar Pahlawan Nasional. Gelar yang dulu tampak mustahil bagi sebagian orang, kini resmi disematkan. Namun sebelum sampai ke titik ini, perjalanan wacana tersebut berliku — penuh perdebatan, emosi, dan pertanyaan moral yang tak mudah dijawab.
Selama lebih dari satu dekade, setiap kali usulan pemberian gelar itu muncul, perdebatan selalu memanas. Bukan karena bangsa ini tidak mengakui jasanya, tetapi karena sejarah Soeharto tidak sesederhana hitam dan putih. Ia memang berperan besar dalam menata negeri pasca-kemerdekaan, menjaga stabilitas, dan membawa pembangunan yang pesat. Tetapi disisi lain, bayang-bayang kelam masa Orde Baru — represi politik, pelanggaran HAM, dan praktik korupsi — masih membekas dalam ingatan kolektif bangsa.
Itulah sebabnya, penundaan selama bertahun-tahun itu bukan semata karena birokrasi atau prosedur administratif. Ia lebih menyerupai jeda moral — masa diam panjang ketika bangsa ini masih belajar berdamai dengan luka dan menimbang ulang makna kepahlawanan.
Dalam berbagai bidang dan kajian, muncul pertanyaan yang tak pernah mudah dijawab:
Apakah seseorang yang punya jasa besar bagi bangsa bisa dihapus dari daftar pahlawan karena dosa politiknya?
Atau sebaliknya, apakah jasa besar itu cukup untuk menutup mata dari kesalahan masa lalu?
Kementerian Sosial dan tim peneliti sejarah beberapa kali menunda keputusan itu karena alasan etis. TAP MPR No. XI/MPR/1998 yang menyebut Soeharto terkait penyelenggaraan negara yang sarat KKN menjadi penghalang hukum sekaligus simbol moral: bahwa bangsa ini belum siap menempatkan beliau di panggung kehormatan sebelum mengakui sisi gelap kepemimpinannya.
Baca Juga: Warga Sukabumi Belum Dapat KIS dan PIP, Jaenudin Ingatkan Pentingnya Peran RT dan RW
Namun waktu berjalan, generasi berganti, dan narasi sejarah pun mulai berubah nadanya.
Kini, pemerintah menilai Soeharto layak mendapatkan gelar itu berdasarkan jasa militernya, keterlibatannya dalam perjuangan pembebasan Irian Barat, serta sumbangsihnya terhadap pembangunan nasional. Tapi di luar keputusan resmi itu, sebagian masyarakat masih bergulat dengan perasaan yang sama: antara menghormati dan mengingat, antara mengakui dan mengoreksi.
Gelar Pahlawan Nasional memang sebuah penghargaan, tetapi bagi bangsa yang masih belajar jujur terhadap masa lalunya, ia juga cermin yang memantulkan pertanyaan lebih dalam:
Apa arti kepahlawanan di mata kita hari ini?
Apakah pahlawan hanya tentang jasa besar, atau juga tentang keteladanan moral yang tak lekang oleh waktu?
Mungkin disanalah letak refleksi terbesar dari penundaan panjang itu. Bahwa bangsa ini tidak menolak jasa seseorang, tetapi sedang belajar menimbang antara keberhasilan dan kemanusiaan. Dan ketika akhirnya waktu memberi ruang bagi gelar itu untuk diberikan, sejarah pun mencatat — bukan hanya tentang siapa yang diberi penghargaan, tetapi juga bagaimana bangsa ini memilih untuk mengingat.