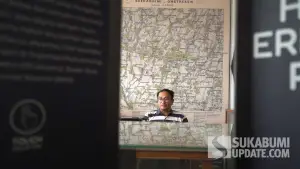SUKABUMIUPDATE.com - Gerakan moshing yang kini kerap memicu kontroversi di konser-konser Indonesia sebenarnya punya akar sejarah panjang dalam dunia musik ekstrem. Awalnya bermula dari gerakan Pogo di era punk London tahun 1970-an, di mana penonton saling melompat dan mendorong sebagai bentuk pemberontakan terhadap kemapanan.
Band seperti Sex Pistols dan The Clash menjadi pelopor gerakan ini, menciptakan atmosfer chaos yang justru dicari oleh penonton punk saat itu.
Memasuki tahun 1980-an, gerakan ini berevolusi menjadi lebih brutal di tangan scene thrash metal Amerika. Istilah "moshing" sendiri berasal dari kata "mash" yang dalam dialek California diucapkan sebagai "mosh".
Baca Juga: Diduga Pukuli Penonton Bawa Bendera One Piece, Awan .Feast Tegur Aparat di RI Fest 2025
Konser-konser band seperti Slayer dan Metallica menjadi tempat lahirnya tradisi circle pit dan wall of death, di mana penonton saling berdesakan dan berlarian dalam formasi melingkar. Adegan-adegan keras ini menjadi ciri khas konser metal yang bertahan hingga kini.
Era 1990-an membawa moshing ke arus utama berkat band seperti Nirvana. Video klip "Smells Like Teen Spirit" memperlihatkan bagaimana gerakan ini menjadi bagian tak terpisahkan dari kultur grunge. Namun, moshing juga mulai menuai kontroversi.
Media massa kerap menyorotnya sebagai aktivitas berbahaya setelah beberapa insiden cedera terjadi, termasuk di konser Pantera yang legendaris. Meski demikian, band seperti Rage Against The Machine justru memanfaatkan energi moshing sebagai simbol perlawanan politik, menunjukkan betapa gerakan ini memiliki dimensi yang lebih dalam sekadar kekerasan.
Baca Juga: Sejarah Para Ratu Metal yang Mengguncang Dunia, Bukan Hanya Sekedar Pemanis
Di Indonesia, tradisi moshing mulai populer seiring dengan berkembangnya scene metal dan hardcore pada tahun 2000-an. Festival seperti Hammersonic dan Java Rockin'Land menjadi saksi bagaimana penonton lokal mengadopsi budaya ini dengan antusias.
Namun, tak jarang terjadi gesekan dengan aparat keamanan yang kurang memahami konteks moshing sebagai bagian dari ekspresi musikal, seperti yang terjadi baru-baru ini di RI Fest 2025.
Moshing modern telah berkembang menjadi lebih beragam. Scene metalcore dan hardcore memperkenalkan variasi seperti two-stepping, sementara elemen seperti crowd surfing dan wall of death tetap menjadi favorit penonton.
Kemudian yang menarik, di balik penampilannya yang keras, moshing memiliki etiket tidak tertulis yang dijunjung tinggi oleh komunitasnya, seperti membantu sesama penonton yang terjatuh atau kehilangan barang.
Kini, moshing tetap menjadi simbol kebebasan berekspresi di dunia musik ekstrem, meski terus menuai pro dan kontra. Seperti yang dikatakan Awan dari .Feast, bagi penikmatnya, moshing bukan sekadar kekerasan, melainkan bahasa tubuh yang tak terpisahkan dari pengalaman menikmati musik secara total.
Bagaimanapun, satu hal yang pasti: selama musik ekstrem masih ada, tradisi moshing akan terus hidup dan berevolusi. Moshing itu seperti api unggun di gurun music terlihat berbahaya, tapi bagi yang paham, ia adalah sumber kehangatan persaudaraan.
Di tengah debu sepatu yang beterbangan dan keringat yang muncrat, ada sebuah bahasa universal yang hanya dimengerti oleh mereka yang berani terjun ke pit: bahwa di balik dorongan dan benturan, yang ada bukanlah amarah, tapi euforia murni.
Jadi ketika melihat kerumunan moshing, jangan buru-buru menghakimi bisa jadi di sanalah orang-orang paling bahagia di seluruh venue sedang merayakan kebebasan, satu hantaman badan ke badan.
Sumber: Berbagai Sumber
Penulis: Danang Hamid