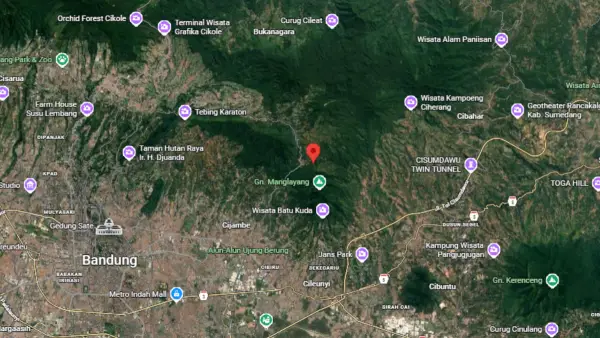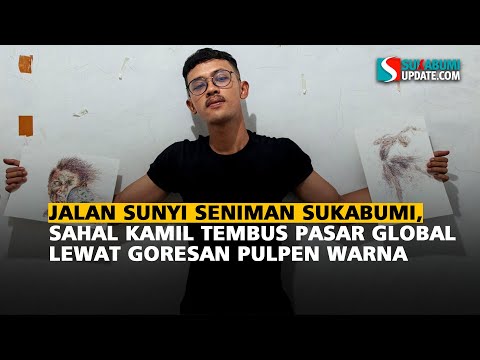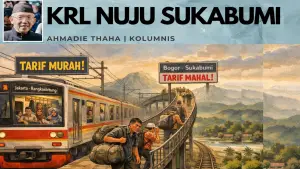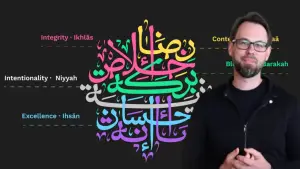SUKABUMIUPDATE.com. - Di era modern ini, siapakah dari Anda yang masih mengenal atau pernah menyentuh dan memainkan Tarawangsa, Updaters? Sebuah alat musik gesek berleher panjang yang menyerupai Rebab, tetapi dengan beberapa ciri khas yang umumnya hanya memiliki dua senar (dawai) yang terbuat dari kawat baja atau besi. Dan instrument musik Sunda ini punya alat pendamping wajib, musabab dalam kesenian Tarawangsa, alat ini selalu dimainkan seirisan dengan Jentreng (sejenis Kecapi kecil dengan 7 senar) yang dimainkan dengan cara dipetik.
Tarawangsa bukanlah sekadar artefak budaya yang dipajang di museum, melainkan sebuah kesenian yang memiliki denyut kehidupan ritual dan spiritual yang kuat di kalangan masyarakat Sunda, khususnya di Jawa Barat. Ia mewakili sebuah sistem kepercayaan kuno (Sunda Wiwitan atau Sunda Buhun) yang berakar pada keselarasan alam dan rasa syukur agraris. Berbeda dari instrumen gesek modern seperti Biola,
Tarawangsa telah ada jauh sebelum era kolonial, bahkan sebelum Rebab diperkenalkan, menjadikannya salah satu instrumen musik tertua dan paling sakral yang pernah dimiliki Tanah Pasundan. Kesenian ini tidak hanya menghadirkan melodi, tetapi juga menghadirkan suasana magis yang berfungsi sebagai jembatan komunikasi spiritual antara manusia yang merayakan dengan leluhur serta Sang Pencipta, terbungkus dalam ritual yang kaya simbol.
Secara linguistik dan filosofis, nama Tarawangsa sendiri adalah kunci untuk memahami peran esensial kesenian ini dalam kosmologi Sunda. Interpretasi yang paling kokoh, didukung oleh studi etnomusikologi, membedah kata ini menjadi tiga suku kata utama, yang masing-masing sarat makna: Ta, Ra, dan Wangsa. Suku kata 'Ta' merupakan akronim dari kata Sunda 'Meta', yang berarti Pergerakan atau proses dinamis kehidupan dan alam. Ini merujuk pada siklus menanam, tumbuh, dan memanen padi.
Suku kata 'Ra' diambil dari bahasa Sanskerta/Arab yang berarti Api Agung atau Matahari, yang dalam konteks agraris Sunda menjadi simbol tertinggi dari sumber kehidupan dan kekuatan Ilahi yang disembah, seringkali diasosiasikan dengan Dewi Sri. Sementara itu, 'Wangsa' diartikan sebagai Bangsa atau komunitas manusia. Dengan demikian, secara komprehensif, Tarawangsa dimaknai sebagai "Kisah Kehidupan Bangsa yang Bergerak dan Bergantung pada Matahari." Filosofi ini menegaskan bahwa seluruh upacara Tarawangsa adalah bentuk ekspresi syukur dan penghormatan setinggi-tingginya kepada alam raya—terutama matahari yang menumbuhkan padi—sebagai simbol karunia Sang Pencipta.
 Beda Tarawangsa dengan alat musik sejenis seperti rebab (Ilustrasi: CnavaAI)
Beda Tarawangsa dengan alat musik sejenis seperti rebab (Ilustrasi: CnavaAI)
Anatomi Musik dan Waditra Keunikan Duet Gesek-Petik
Kekhasan Tarawangsa terletak pada struktur ansambelnya yang minimalis namun sarat peran. Kesenian ini, khususnya yang murni dari wilayah pelestari utama seperti Rancakalong, Sumedang, hanya melibatkan dua instrumen utama yang dimainkan oleh dua orang: Tarawangsa itu sendiri dan Jentreng.
Instrumen Tarawangsa (Ngek-ngek): Alat gesek ini secara fisik menyerupai rebab yang lebih tinggi, bahkan dijuluki Rebab Jangkung. Keunikannya adalah memiliki dua senar (dawainya terbuat dari kawat baja atau besi) yang dimainkan dengan cara berbeda. Senar pertama, yang disebut dengdeng, digesek untuk membawakan melodi utama dan ornamentasi yang rumit, menghasilkan bunyi yang mendayu dan serak (ngek-ngek). Sedangkan senar kedua, yang disebut dengduk atau pupunden, tidak digesek tetapi dipetik secara ritmis oleh jari telunjuk pemain tangan kiri. Pemisahan fungsi gesek (melodi) dan petik (ritme/gong) dalam satu instrumen ini merupakan teknik yang sangat jarang dan membutuhkan penguasaan spiritual dan teknis yang tinggi. Posisinya dimainkan vertikal (tegak), diletakkan di lantai atau digantung rendah, tidak seperti Biola yang disandarkan di bahu.
Baca Juga: Padi Reborn Rilis Single "Ego" dan Album "Dua Delapan" Jumat, 7 November 2025
Jentreng (Kacapi Tarawangsa): Merupakan alat musik petik pengiring yang mirip kecapi, tetapi ukurannya lebih kecil dan hanya memiliki tujuh senar. Jentreng berfungsi sebagai pemberi anggeran wiletan (ketetapan ritme) dan irama.
Karakter Musikal: Musik Tarawangsa disajikan dalam laras Pelog atau Salendro. Melodi yang dibawakan sangat lambat, penuh improvisasi (ornamentasi), dan mengutamakan 'rasa' (perasaan batin) daripada ketepatan notasi baku, sehingga alunan yang dihasilkan memiliki nuansa mistis, sendu, dan hipnotis yang bertujuan memancing suasana hening dan kontak spiritual.
Jantung Keseimbangan Kosmos & Jiwa Agraris Sunda
Fungsi Tarawangsa tidak pernah lepas dari dimensi sakral, menjadikannya salah satu praktik ritual terpenting dalam budaya Sunda. Tarawangsa adalah musik inti yang mengiringi upacara-upacara terkait siklus padi, yang paling terkenal adalah Seren Taun (syukuran panen raya) dan Ngalaksa (ritual pengolahan padi). Kesenian ini dimainkan untuk menghormati Dewi Sri dan memohon keselamatan serta berkah agar panen selanjutnya berlimpah. Dipercaya, jika upacara ini tidak dilaksanakan, akan terjadi mala petaka pada musim tanam berikutnya.
Tarian trance atau ngibing adalah bagian klimaks dan paling magis dari pertunjukan Tarawangsa. Diiringi alunan yang semakin intens dan mendayu, penari, yang seringkali merupakan tokoh adat (Saehu untuk pria dan Paibuan untuk wanita), mulai menari secara spontan (ngibing) hingga beberapa di antaranya memasuki kondisi trance (kesurupan). Kondisi ini diyakini sebagai momen ketika roh leluhur atau Dewi Sri turun dan berkomunikasi melalui tubuh penari. Penari tersebut kemudian menyampaikan pesan, nasihat, atau doa kepada komunitas.
Seluruh ritual Tarawangsa diyakini menjaga konsep Tritangtu (Trinitas) Sunda, yaitu keseimbangan antara Buana Nyungcung (Dunia Atas/Tuhan), Buana Panca Tengah (Dunia Manusia), dan Buana Larang (Dunia Bawah/Alam). Musik Tarawangsa berfungsi sebagai benang penghubung agar tiga alam ini tetap harmonis, memastikan kehidupan manusia mendapat berkah dari Tuhan dan alam.
Meskipun kesenian Tarawangsa semakin jarang ditemui dan kini didominasi oleh komunitas tertentu (seperti di Rancakalong, Sumedang, dan beberapa daerah di Tasikmalaya dan Bandung), ia telah diakui sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) Indonesia. Di era modern, Tarawangsa menghadapi tantangan besar, di mana generasi muda cenderung melihatnya sebagai musik horor atau mistis karena asosiasinya dengan trance dan sesajen, menjauhi konteks ritualnya.
Namun, beberapa kelompok mulai memodifikasi Tarawangsa untuk kepentingan hiburan dan komersial, menambahkan instrumen modern atau mengubah struktur lagu, yang berisiko menghilangkan kesakralan dan keaslian filosofisnya. Tetapi, di komunitas aslinya, para nayaga (pemain musik) dan saehu terus menjaga tradisi ini dengan ketat. Bagi mereka, Tarawangsa bukan sekadar warisan, tetapi "doa yang dimainkan" sebuah identitas kolektif dan janji untuk terus bersyukur atas karunia Sang Pencipta melalui kesuburan Tanah Sunda.