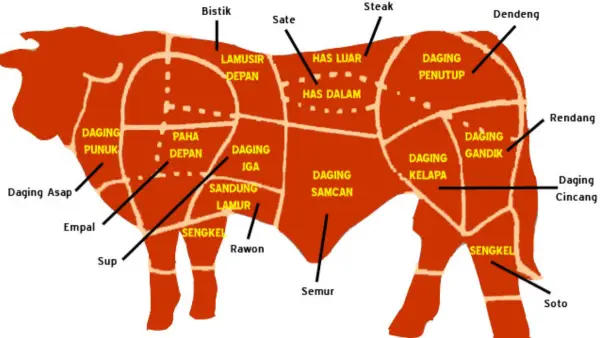SUKABUMIUPDATE.com - Ada keyakinan mendalam di sebagian masyarakat Sunda, terutama generasi tua, yang melarang perempuan Sunda menikah dengan laki-laki Jawa. Larangan ini bukan tanpa sebab, melainkan berakar pada Tragedi Bubat abad ke-14.
Inti mitos ini adalah kegagalan pernikahan politik antara Dyah Pitaloka dari Kerajaan Sunda dan Hayam Wuruk dari Majapahit. Rencana damai ini berubah menjadi tragedi berdarah di Lapangan Bubat. Patih Majapahit, Gajah Mada, diyakini menuntut Putri Dyah Pitaloka sebagai tanda ketundukan (takluk) Kerajaan Sunda, bukan sebagai permaisuri. Akhirnya, sang putri dan rombongan memilih bunuh diri (bela pati) demi mempertahankan kehormatan dan martabat. Namu, Perlu ditekankan, sejarah hadir sebagai cermin, bukan sebagai pedang.
Dari peristiwa inilah lahir keyakinan bahwa pernikahan Sunda-Jawa akan mengulang trauma sejarah, di mana perempuan Sunda dianggap sebagai "tumbal" atau simbol penyerahan diri. Larangan ini berfungsi sebagai benteng untuk melestarikan identitas budaya Sunda dari hegemoni Jawa.
Di masa kini, meski banyak pasangan Sunda-Jawa hidup harmonis, sisa-sisa keyakinan ini masih berpengaruh. Banyak generasi muda Sunda yang harus berdialog dengan orang tua mereka ketika memilih pasangan dari Jawa, kerap diingatkan untuk "belajar dari sejarah" agar tidak mengulang aib nenek moyang di Bubat.
Baca Juga: The Neighbourhood Siap Guncang Jakarta dalam 'The Wourld Tour' 2026!
 Tabu pernikahan Sunda-Jawa: bukan soal cinta, tapi luka Gajah Mada yang mengubah mempelai menjadi persembahan. Sebuah janji kehormatan (Foto:Canva).
Tabu pernikahan Sunda-Jawa: bukan soal cinta, tapi luka Gajah Mada yang mengubah mempelai menjadi persembahan. Sebuah janji kehormatan (Foto:Canva).
Sultan Agung Simbol Hegemoni yang Menguatkan Mitos
Ketika Majapahit perlahan surut dan Kerajaan Sunda (Pajajaran) telah runtuh, estafet hegemoni politik Jawa beralih kepada Kesultanan Mataram, yang dipimpin oleh tokoh karismatik namun keras, Sultan Agung Hanyokrokusumo. Meskipun Sultan Agung hidup berabad-abad setelah Gajah Mada, ia secara efektif menjadi simbol baru dari upaya sentralisasi dan penundukan politik Jawa atas wilayah Priangan.
Dalam narasi lisan rakyat Sunda, kebijakan Sultan Agung yang tanpa kompromi termasuk tuntutan upeti, penempatan pejabat, dan kekerasan yang ia tunjukkan terhadap para bupati Sunda (seperti kisah tragis Dipati Ukur) secara ironis memperkuat kembali narasi ketidakpercayaan yang pertama kali ditanamkan di Bubat. Kisah-kisah ini mematrikan persepsi bahwa setiap kekuasaan besar dari timur pasti akan membawa ancaman terhadap martabat dan otonomi lokal.
Peran Sultan Agung dalam konteks ini sangatlah esensial karena ia memberikan pembenaran historis yang berkelanjutan bagi trauma Bubat. Jika Bubat adalah luka pertama yang disebabkan oleh ambisi, maka penindasan Mataram adalah luka kedua yang membuktikan bahwa ancaman dominasi adalah pola yang berulang, bukan sekadar insiden tunggal.
 Alih-alih meratapi kekalahan heroik akibat arogansi eksternal Majapahit seperti yang dilakukan Kidung Sunda, naskah ini justru menempatkan akar bencana pada pihak Sunda sendiri, khususnya pada sang Putri dan Raja (Ilustrasi: Sora).
Alih-alih meratapi kekalahan heroik akibat arogansi eksternal Majapahit seperti yang dilakukan Kidung Sunda, naskah ini justru menempatkan akar bencana pada pihak Sunda sendiri, khususnya pada sang Putri dan Raja (Ilustrasi: Sora).
Dengan demikian, meskipun di Jawa Sultan Agung dihormati sebagai pahlawan yang menyatukan wilayah, di Priangan ia kerap muncul sebagai figur yang menekan dan menuntut kepatuhan. Konsekuensinya, narasi kultural bahwa ikatan emosional (pernikahan) dengan entitas politik yang secara historis dominan hanya akan mendatangkan kerugian dan ancaman terhadap martabat semakin mengakar kuat, mengubah tabu pernikahan menjadi sebuah pertahanan budaya yang logis bagi masyarakat Sunda.
Tabu yang Lahir dari Pengorbanan dan Kehormatan
Mitos ini adalah semacam monumen tak terlihat yang dibangun dari darah dan kehormatan. Dalam narasi populer, larangan ini muncul karena pernikahan Dyah Pitaloka dengan Hayam Wuruk berujung tragedi akibat ambisi politik Gajah Mada. Alih-alih menjadi permaisuri, sang putri dikorbankan sebagai "upeti." Pilihan bela pati sang putri menjadi simbol perlawanan terakhir. Bagi ingatan kolektif Sunda, pernikahan dengan pihak Jawa kerap dihubungkan dengan trauma masa lalu, di mana perempuan dijadikan simbol penyerahan kedaulatan. Tabu ini menjadi mekanisme pertahanan budaya jika politik telah merenggut kehormatan, maka adat bertugas menjaganya.
Meskipun dalam realitas modern tabu ini semakin menipis, mitos Bubat tetap hidup sebagai topik reflektif, terutama di kalangan generasi tua. Bagi sebagian orang, larangan ini adalah pengingat sepanjang zaman tentang harga diri yang dipertaruhkan di Lapangan Bubat, menciptakan "jarak kultural" yang dianggap perlu untuk menegaskan identitas.
Apapun interpretasinya apakah warisan dendam sejarah atau konstruksi sosial pascakerajaan, Mitos Bubat membuktikan betapa dampak emosional sebuah tragedi politik dapat membentuk tatanan sosial selama berabad-abad. Tragedi Bubat adalah luka sejarah yang melampaui catatan politik; ia telah meresap jauh ke dalam nalar dan memori kultural. Narasi ini mengubah kekalahan politik di medan perang menjadi kekalahan batin yang diabadikan dalam adat. Sekali lagi! Sejarah hadir sebagai cermin, bukan sebagai pedang. Hubungan Sunda-Jawa kini telah berkembang dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Pelajaran terpenting dari Bubat bukanlah untuk melestarikan prasangka, tetapi untuk memahami cara kerja memori kolektif, sehingga dapat membangun hubungan antarbudaya yang lebih inklusif dan saling menghargai.