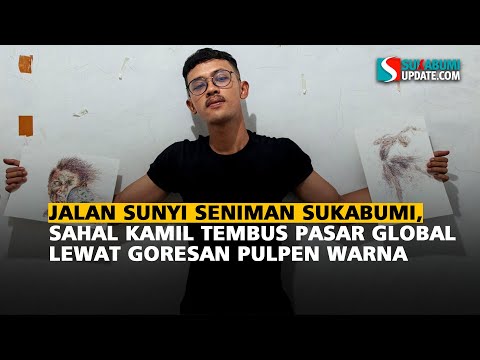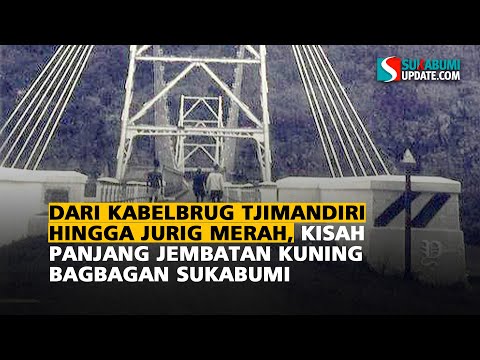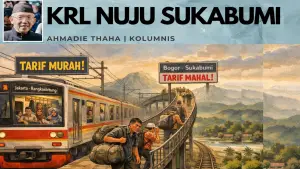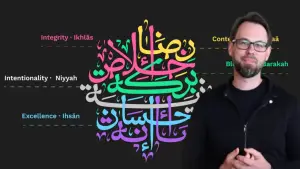SUKABUMIUPDATE.com - Setelah menelusuri narasi pilu Kidung Sunda yang menyalahkan arogansi Mahapatih Gajah Mada dan perbandingan kontrasnya dengan Carita Parahyangan yang justru mengkritik ambisi internal Putri Sunda (Tohaan), kita dapat menyimpulkan bahwa Peristiwa Bubat bukan sekadar catatan sejarah, melainkan sebuah epilog yang membentuk memori kultural Tanah Sunda.
Kisah cinta yang berubah menjadi medan pertempuran ini secara fundamental mengajarkan tentang nilai siri (harga diri) yang tak ternilai, mengingatkan bahwa kekuatan imperium seperti Majapahit dapat runtuh oleh kehancuran hati dan ambisi politik yang tak terkendali.Tragedi ini menjadi monumen perlawanan terhadap hegemoni dan peringatan mendalam tentang betapa rapuhnya kedaulatan ketika ego mengalahkan akal sehat, meninggalkan warisan yang hingga kini termanifestasi dalam mitos pantang kawin antara suku Sunda dan Jawa.
Perspektif unik yang disajikan dalam naskah Sunda Kuno, Carita Parahyangan, mengenai Tragedi Bubat adalah anomali yang signifikan. Alih-alih meratapi kekalahan heroik akibat arogansi eksternal Majapahit seperti yang dilakukan Kidung Sunda, naskah ini justru menempatkan akar bencana pada pihak Sunda sendiri, khususnya pada sang Putri dan Raja.
Baca Juga: Wangsit Siliwangi Apakah Sekadar Ramalan atau Panggilan Moral dari Tanah Pasundan?
Carita Parahyangan yang utamanya berfungsi sebagai catatan silsilah raja-raja Sunda dan pedoman moral-politik bagi penguasa menggunakan tragedi ini sebagai contoh kegagalan internal yang harus dihindari oleh generasi berikutnya. Naskah ini mengisahkan bahwa Raja Sunda (Prabu Maharaja) terperangkap dalam musibah (kabawa ku kalawisaya) yang dipicu oleh sesuatu yang seharusnya menjadi kebahagiaan: pernikahan keturunannya.
 Carita Parahyangan Perspektif unik yang disajikan dalam naskah Sunda Kuno, Carita Parahyangan, mengenai Tragedi Bubat adalah anomali yang signifikan (Foto ilustasi: CanvaAI)
Carita Parahyangan Perspektif unik yang disajikan dalam naskah Sunda Kuno, Carita Parahyangan, mengenai Tragedi Bubat adalah anomali yang signifikan (Foto ilustasi: CanvaAI)
Menta Gede Pameulina
Inti dari kritik Carita Parahyangan terletak pada klaim bahwa Putri Sunda, yang dijuluki Tohaan (yang dihormati), memiliki keinginan yang terlampau besar (mundut agung dipapanumbasna atau menta gede pameulina). Secara naratif, "keinginan besar" ini ditafsirkan sebagai hasrat yang ambisius dan melanggar batas etika: sang Putri ingin menikah dengan Raja Agung Majapahit penguasa imperium terkuat saat itu sekaligus secara implisit menolak untuk bersuami orang Sunda sendiri (mumul nu lakian di Sunda).
Dalam konteks politik dan kultural Sunda Kuno, di mana menjaga kedaulatan berarti membatasi pengaruh eksternal, hasrat untuk menikah dengan penguasa asing dari Jawa Timur yang berpotensi mengancam hegemoni dianggap sebagai tindakan mengabaikan kearifan lokal dan mengkhianati tatanan sosial-politik. Naskah ini menjadikannya pelajaran bahwa ambisi pribadi, sekecil apa pun, jika mengabaikan prinsip negara dapat berakibat fatal.
Baca Juga: Markas Pejuang RI di Bandung, Sejarah Museum Mandala Wangsit Siliwangi Jawa Barat
Kehancuran Akibat Pelanggaran Adat dan Etika Politik
Dengan menyebutkan bahwa Putri Sunda menolak suami lokal, Carita Parahyangan menekankan pentingnya endogami politik (menikah dalam lingkungan internal kerajaan atau aliansi yang setara) demi menjaga keutuhan dan kedaulatan negara. Kepergian rombongan Sunda ke Majapahit untuk melangsungkan pernikahan di sana, alih-alih di Kerajaan Sunda sesuai tradisi, dilihat sebagai langkah ceroboh dan kecerobohan politik yang dilakukan oleh Prabu Maharaja.
Dalam pandangan naskah ini, tragedi Bubat terjadi karena Raja Sunda gagal mengendalikan hasrat pribadi dan ambisi politik putrinya yang ingin melampaui batas, beliau seharusnya lebih tegas dalam menjaga wibawa kerajaan. Ini adalah kontras tajam dengan Kidung Sunda yang menempatkan arogansi Gajah Mada sebagai pemicu, karena Carita Parahyangan berfokus pada tanggung jawab internal, bencana datang bukan dari kekuatan musuh, melainkan dari kesalahan perhitungan dan keinginan yang berlebihan di pihak sendiri.
Perbedaan narasi ini mengungkapkan fungsi utama dari Carita Parahyangan . Naskah ini tidak ditulis untuk membangun sentimen anti-Jawa pasca-tragedi, melainkan untuk memberikan nasihat moral-politik yang keras kepada para raja Sunda di masa depan.
Baca Juga: Sang Penakluk! Fatahillah dan Portugis dalam Catatan Sejarah Sunda Kelapa
Peristiwa Bubat digunakan sebagai pembelajaran pahit (sebuah warning) bahwa kedaulatan politik dan martabat kerajaan (kasundaan) harus diutamakan di atas segala hasrat romantis, ambisi pribadi, atau kesalahan diplomasi. Dengan menyalahkan pihak internal, naskah ini mengingatkan penerus tahta Pajajaran agar selalu waspada terhadap godaan kekuasaan besar dan menjaga kearifan lokal. Dengan demikian, meskipun hasilnya sama-sama tragis, perspektif Carita Parahyangan lebih bersifat introspektif dan didaktik daripada narasi elegi heroik yang disajikan oleh Kidung Sunda .
Tragedi Bubat, baik yang memuji pengorbanan (Kidung Sunda) maupun yang mengkritik hasrat pribadi (Carita Parahyangan), bersumber dari tradisi sastra yang berbeda namun saling melengkapi.Naskah Kidung Sunda, yang ditulis dalam bahasa Jawa Pertengahan berbentuk tembang (syair) ini menariknya ditemukan di Bali, dan kemungkinan besar disusun oleh penulis dari Bali atau Jawa sebagai narasi yang mengutuk arogansi Majapahit dari sudut pandang yang lebih netral atau pro-Sunda. Sementara itu, naskah Carita Parahyangan, ditulis menggunakan aksara Sunda Kuno pada daun lontar di Tatar Sunda sendiri (Jawa Barat) sekitar akhir abad ke-16, menjadi dokumen penting yang kini tersimpan di Museum Nasional Indonesia (Kropak 406), berfungsi sebagai pencatatan sejarah dan pedoman moral bagi Kerajaan Sunda, yang menjadikannya sebagai kritik internal yang otentik dari dalam kebudayaan Sunda itu sendiri.