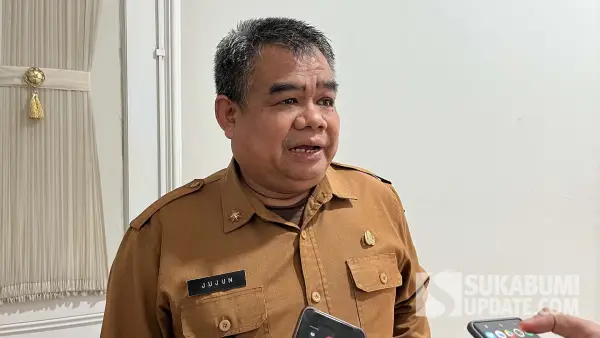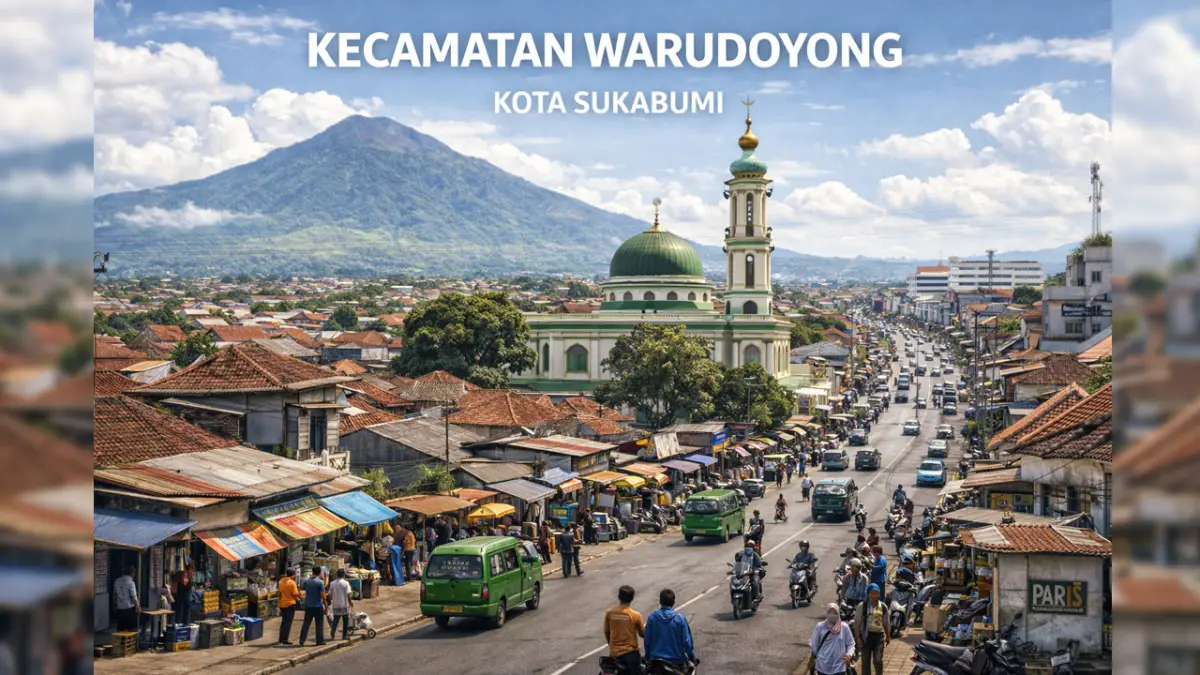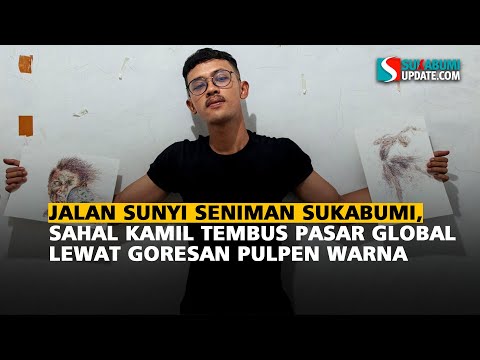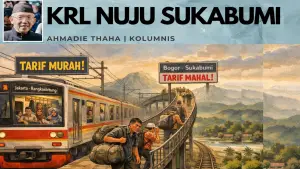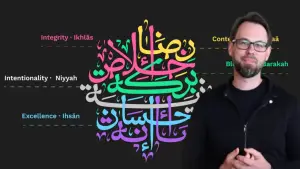SUKABUMIUPDATE.com - Di antara kekayaan naskah kuno Nusantara, tersemat sebuah epos pilu yang terus menggema sepanjang zaman Kidung Sunda. Sebuah mahakarya sastra Jawa-Bali yang mengabadikan tragedi berdarah yang mengubah peta hubungan dua kerajaan adidaya di Tanah Jawa, Majapahit dan Sunda Galuh.
Hal pertama yang sering menimbulkan kebingungan adalah identitas kultural naskah itu sendiri. Meskipun secara eksplisit berkisah tentang Kerajaan Sunda di Jawa Barat, seluruh naskah yang ditemukan justru ditulis dalam bahasa Jawa Pertengahan dan dilestarikan oleh pujangga di Bali.
Fenomena ini bukan hanya menunjukkan eratnya koneksi kultural Jawa-Bali, tetapi juga menyiratkan adanya jarak naratif kisah ini mungkin ditulis oleh pihak yang simpati tetapi bukan bagian langsung dari Kerajaan Sunda, menjadikannya sebuah memori bersama Nusantara yang terpelihara secara unik di luar tanah asalnya.
Kidung Narasi dari Balik Tirai
Kidung Sunda bukan sekadar cerita biasa. Ia adalah sebuah kidung genre sastra berbentuk syair naratif yang dilagukan yang lahir dari tradisi sastra Jawa Kuno dan Pertengahan. Judul "Kidung Sunda" sendiri bermakna "Nyanyian tentang Kisah Sunda," menyiratkan bahwa ini adalah perspektif luar yang merangkai kisah tragis yang menimpa kerajaan dari Jawa Barat tersebut.
Fakta bahwa naskah-naskah Kidung Sunda yang kita kenal semua ditemukan di Bali menjadi bukti kuat. Para pujangga Bali berperan penting dalam melestarikan warisan sastra Jawa setelah keruntuhan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Jawa, menjadikannya salah satu mata rantai penting sejarah kultural Nusantara.
Mahkota yang Dipaksa Menjadi Upeti
Kisah kelam ini berawal dari niat baik dan romantisme politik. Raja Hayam Wuruk dari Majapahit penguasa ambisius dari sebuah imperium yang tengah jaya berhasrat meminang Dyah Pitaloka Citraresmi, putri mahkota Kerajaan Sunda Galuh yang masyhur kecantikannya.
Rombongan Sunda pun berangkat menuju timur, dipimpin langsung oleh sang Raja (disebut Prabu Maharaja dalam naskah) dan diiringi rombongan besar, penuh harap akan sebuah pernikahan agung yang menyatukan dua entitas politik besar.
Baca Juga: CEK FAKTA: Link Pemutihan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) itu Hoaks!
Namun, di balik wajah ramah diplomasi, tersimpan manuver politik yang kejam. Mahapatih Gajah Mada, arsitek utama kejayaan Majapahit, melihat momentum ini sebagai kesempatan emas untuk mewujudkan Sumpah Palapanya secara total. Bagi sang mahapatih, pernikahan ini bukan urusan cinta, melainkan harus menjadi simbol takluknya Kerajaan Sunda di bawah hegemoni Majapahit.
Pertumpahan Darah di Lapangan Bubat
Rombongan Kerajaan Sunda ditempatkan di Lapangan Bubat, sebuah padang di gerbang masuk ibu kota Majapahit. Di sinilah bencana diplomasi yang tak terhindarkan itu meletus.
Gajah Mada menyampaikan tuntutan yang menusuk: bahwa kedatangan Raja Sunda harus diartikan sebagai penyerahan diri dan Dyah Pitaloka sebagai upeti kepada Majapahit. Ini adalah penghinaan fatal yang tak bisa ditelan oleh Raja Sunda, yang menjunjung tinggi harga diri dan kehormatan ksatria di atas segalanya.
Prinsip yang dipegang teguh pun ditetapkan: "Lebih baik gugur sebagai ksatria sejati daripada hidup dalam kenistaan sebagai taklukan." Pilihan sulit pun diambil: bertarung demi kehormatan kerajaan, meskipun mereka tahu akan kalah jumlah.
Pertempuran tak seimbang pun pecah di Lapangan Bubat. Pasukan kecil dari Sunda bertarung dengan gagah berani melawan bala tentara Majapahit yang jauh lebih superior. Satu per satu ksatria Sunda berguguran, termasuk sang raja.
Melihat kehormatan keluarga dan negaranya runtuh, Dyah Pitaloka memilih jalan terhormat: bela pati bunuh diri untuk menjaga kesucian dan martabatnya sebagai putri raja dan menjauhkan diri dari kemungkinan diperistri sebagai rampasan.
Kidung Sunda Jembatan Antara Sastra dan Sejarah
Penting untuk mencermati posisi Kidung Sunda dalam historiografi. Karya ini adalah artefak sastra, bukan catatan sejarah faktual. Sumber resmi Majapahit, seperti Nagarakertagama karya Mpu Prapanca yang ditulis untuk memuliakan Hayam Wuruk sama sekali tidak mencatat peristiwa tragis dan memalukan ini.
Namun, justru inilah nilai adiluhung Kidung Sunda. Ia menyajikan perspektif alternatif, suara dari pihak yang kalah, yang sengaja dibungkam atau dihilangkan dari narasi resmi penguasa. Layaknya sebuah roman sejarah, Kidung Sunda mengangkat sisi humanis dan emosional dari sebuah peristiwa politik berdarah.
Kehormatan dan Pelajaran Moral
Tragedi Bubat meninggalkan jejak mendalam dalam memori kultural Nusantara. Bagi masyarakat Sunda, kisah ini diabadikan sebagai bukti keteguhan prinsip dan siri (harga diri) yang tak bisa ditawar. Sementara itu, dalam tradisi Jawa, kisah ini menjadi pelajaran moral tentang bahaya ambisi politik yang melampaui batas etika.
Fakta unik bahwa kisah yang berlatar Jawa Timur dan menceritakan tentang Sunda ini paling terpelihara di Bali menunjukkan kompleksitas dan interkoneksi jaringan kultural Nusantara kuno.
Maka, Kidung Sunda dapat disimpulkan sebagai monumen naratif humanis yang paling berharga. Ia tidak hanya mengenang kematian heroik sepasukan ksatria, tetapi juga menegaskan nilai luhur budaya Sunda yang menganggap kehormatan (kasundaan) jauh lebih berharga daripada nyawa atau takhta. Dalam setiap baitnya, tersirat kritik tajam terhadap arogansi kekuasaan Majapahit yang nyaris tak terbatas. Kidung ini membuktikan bahwa, meskipun narasi resmi mungkin ditulis oleh pemenang, memori kolektif dan penghormatan terhadap martabat akan selalu menemukan cara untuk hidup melalui karya sastra.
Baca Juga: 7 Daftar Rekomendasi Lagu-Lagu Unplugged Terbaik Sepanjang Masa, Take on Me A-ha Mantap!
Berikut adalah cuplikan kecil dari Kidung Sunda (dalam bentuk alih aksara Latin) yang menggambarkan permulaan tragedi, ketika Raja Sunda marah mendengar tuntutan Gajah Mada.
Teks dalam Bahasa Jawa Kuna:
"Lawan wadwa bhakti nira, sang rajaputri sakeng nagara Sunda, lwir nira sang nrpa Sunda, sira ta pinaraning wadwa, mangastuti rajaputri, mangde sang nrpa Sunda angundangi, ring yuda haji Sunda."
Terjemahan Bahasa Indonesianya (kurang lebih):
"Dan para prajuritnya yang setia, sang putri raja dari negeri Sunda, ayahnya adalah raja Sunda, dia (sang putri) dikawal oleh prajurit, untuk mengantarkan sang putri raja, namun sang raja Sunda justru diajak bertempur, dalam perang raja Sunda."
Cuplikan ini menggambarkan titik balik di mana kunjungan damai berubah menjadi undangan untuk bertempur. Dan, kisah Kidung Sunda pada akhirnya lebih dari sekadar catatan konflik antara dua kerajaan. Ia adalah cermin abadi tentang betapa rapuhnya jalan diplomasi ketika ambisi dan harga diri saling berbenturan. Di atas lapangan Bubat, cinta dan politik bukan lagi sekadar permainan takhtaL, melainkan pertaruhan nyawa dan kehormatan yang berakhir dengan tragedi. Kidung ini mengajarkan bahwa sejarah sering kali ditulis oleh mereka yang bertahan, namun kebenaran dan duka sebuah peristiwa dapat hidup terus dalam bentuk puisi, nyanyian, dan ingatan kolektif yang tak pernah benar-benar padam.
Baca Juga: Meski Ditahan Imbang Nottingham Forest, Ruben Amorim Puji Para Pemain Manchester United
Jika Anda ingin membaca teks lengkapnya, Anda perlu mencari publikasi akademis. Beberapa referensi kunci adalah:
-
Karya Prof. C.C. Berg (1930): "Kidung Sunda. Inleiding, tekst, vertaling en aanteekeningen" yang berisi teks, terjemahan bahasa Belanda, dan komentar.
-
Karya Prof. S. Supomo (1977): "Arjunawijaya. A kakawin of Mpu Tantular" dan berbagai artikelnya sering membahas Kidung Sunda dan menyertakan cuplikan teks.
-
Penerbitan Lokal: Terkadang lembaga seperti Balai Bahasa atau universitas (misalnya Udayana, Bali) menerbitkan edisi kritik dan terjemahan ke dalam bahasa Indonesia untuk kepentingan akademis.
Hingga kini, Kidung Sunda tetap menggema, bukan sebagai pembuka luka lama, melainkan sebagai pengingat akan kompleksitas hubungan manusia. Ia adalah warisan sastra yang melampaui batas geografis dan budaya, menyatukan Jawa, Sunda, dan Bali dalam sebuah narasi pilu yang sama. Cerita ini mengajak kita untuk senantiasa merenungkan betapa sering sebuah niat baik kandas oleh kesalahpahaman, dan betapa mahal harga sebuah kehormatan di mata sejarah.