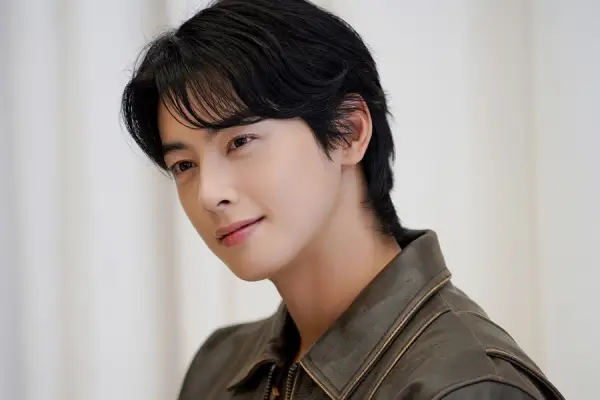Ditulis: Danang Hamid
Ruang Bermusik 2025 di Tasikmalaya, yang rencananya digelar pada 19-20 Juli 2025 di Lanud Wiriadinata , mendadak menjadi sorotan panas. Penyebabnya, tak lain adalah batalnya rencana penampilan Hindia di kota yang dijuluki Kota Santri itu.
Sepekan sebelum acara, sekelompok masyarakat yang menamakan diri Aliansi Aktivis dan Masyarakat Muslim Tasikmalaya atau Al Mumtaz menolak kehadiran Hindia, dengan tuduhan aksi panggungnya "melanggar norma agama" dan "menyebarkan nilai kekufuran".
Proyek solo Baskara, vokalis .Feast (Dengan Titik) dan Lomba Sihir ini, karyanya dikenal dengan lirik personal, puitis, dan kerap menyentuh isu sosial serta kesehatan mental. Tak heran, generasi muda zaman now sangat akrab dengan lagu-lagu Hindia karena dirasa mewakili kondisi mereka.
Beberapa lagu hits-nya seperti "Rumah Ke Rumah", "Secukupnya", dan "Evaluasi" telah menjadi soundtrack bagi banyak anak muda. Namun, yang jadi masalah adalah gestur dan simbol dalam pertunjukannya , seperti patung dan gerakan menutup mata sebelah saat peluncuran album "Lagipula Hidup Akan Berakhir" (2023).
Pola Penolakan yang Berulang
Batalnya Hindia Manggung ini bukan pertama kalinya, konser Hindia pernah pula dibatalkan karena tekanan kelompok tertentu. Sebelumnya, konsernya di Banda Aceh (18 Juni 2025) juga gagal digelar setelah media lokal menuduhnya sebagai "musisi bertema satanik". Meski izin sempat dikeluarkan ulang oleh DPMPTSP, Polresta Banda Aceh menolak memberi rekomendasi, memaksa pembatalan.
Ada dua narasi yang bertolak belakang dengan kejadian ini. Pertama, kelompok penolak yang menganggap simbol di panggung Hindia sebagai ancaman moral dan agama. Mereka menuntut pembatalan dengan alasan "melindungi masyarakat dari pengaruh negatif".
Kedua, pendukung dan panitia. Di mana Rizki Ginanjar Saputra (panitia) menyatakan kepada sejumlah media bahwa aksi kontroversial itu hanya bagian dari konsep album lama dan sudah diklarifikasi.
Sementara itu, Asep Rizal Asari (Ketua Forum Bhinneka Tunggal Ika Tasikmalaya) menegaskan bahwa festival ini sejalan dengan citra Tasikmalaya sebagai "kota event toleran" yang mendukung kreativitas dan ekonomi lokal.
Akar Masalah, Apakah Salah Paham atau Ketidakmauan Berdialog?
Persoalan ini bukan sekadar tentang musik, melainkan benturan antara kebebasan berekspresi dan penafsiran nilai-nilai agama. Kelompok penolak melihat simbol di panggung sebagai ancaman, sementara pendukung menganggapnya sebagai bagian dari ekspresi seni yang perlu dipahami konteksnya.
Dialog terbuka antara musisi, panitia, dan kelompok penolak bisa menjadi jalan keluar. Pemerintah setempat perlu mengambil peran sebagai mediator, bukan sekadar menunggu tekanan massa.
Literasi seni dan edukasi publik tentang konteks pertunjukan musik bisa mencegah kesalahpahaman di masa depan. Jika tidak ada upaya serius untuk mendamaikan kedua kubu, kasus seperti ini akan terus berulang mematikan ruang kreativitas sekaligus mengikis toleransi.
Pertanyaannya, haruskah seni dikorbankan karena penafsiran sepihak? Bagaimana menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan penghormatan terhadap nilai lokal? Satu hal yang pasti bahwa seni dan norma tak harus selalu bertentangan asal ada kemauan untuk saling mendengar.