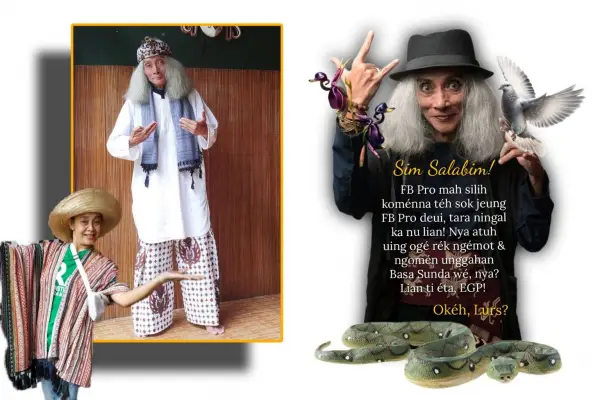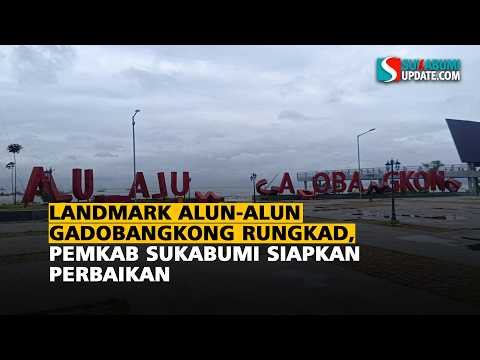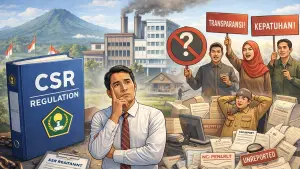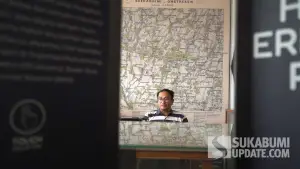SUKABUMIUPDATE.com - Dalam nafas kebudayaan Sunda, terdapat sebuah filosofi agung yang menjadi pondasi kehidupan sosial, berupa Mulang Tarima. Secara harfiah berarti mengembalikan penerimaan atau membalas budi, filosofi ini diwujudkan dalam tradisi Nyambungan. Lebih dari sekadar memberi amplop, Nyambungan adalah ritual pengukuhan tali duduluran (persaudaraan), sebuah komitmen dan tanggung jawab untuk silih tulungan (saling menolong) saat balai (musibah) atau hajat (acara besar) datang.
Di sudut-sudut kampung Majalengka hingga Kuningan pada era 80-an dan 90-an, Nyambungan adalah denyut kehidupan rereongan (gotong royong). Para tamu datang membawa pangéling (kenang-kenangan) atau panyécep (sumbangan) sebelum sebuah hajatan dihelat baik itu hajat pernikahan atau sunatan, panyambung-panyambung itu dicatat rapi dalam buku panambih. Catatan itu bukan sekadar daftar tamu, melainkan dokumen vital yang mencatat utang sosial, menjamin bahwa Mulang Tarima akan terlaksana sempurna di masa depan.
Namun, indahnya Mulang Tarima memiliki sisi gelapnya. Kisah pilu tentang seorang Nenek yang bercerita kepada penulis, ia terpaksa menggadaikan beberapa helai kain pusaka di Pegadaian Kadipaten hanya agar ia tidak ngalangkungan (melewatkan) kewajiban nyambungan adalah gambaran tragis. Kain atau samping biasanya bermotif batik kala itu adalah barang yang cukup berharga ditata rapi dalam lemari dan diperlakukan istimewa. Bagi Nenek itu, dan bagi banyak kaum papa, kehormatan sosial dan rasa malu karena dianggap teu mulang tarima (tidak tahu membalas budi) jauh lebih menakutkan daripada kesulitan ekonomi sesaat. Kain gadai itu adalah mahar yang dibayarkan demi menjaga citarasa (harga diri) di hadapan pangeusi lembur (penghuni kampung).
Baca Juga: Jenis-Jenis Tumbler dan Kegunaannya, Mana yang Paling Cocok untukmu?
Kisah-kisah ini menunjukkan bahwa di tengah masyarakat yang memegang teguh adat, Nyambungan bukanlah lagi pilihan, melainkan kewajiban sosial yang mengikat. Sistem ini beroperasi layaknya sebuah "Arisan Wajib Bayar" yang cakupannya seumur hidup. Ketika Sohibul Hajat menerima sumbangan, mereka secara tidak langsung mengumpulkan daftar utang budi. Tekanan terberat justru dirasakan oleh mereka yang secara ekonomi paling lemah. Mereka harus memastikan balasan yang diberikan setara atau lebih dari yang diterima, agar ketika mereka sendiri berhajat, bantuan akan mengalir kembali. Ini adalah investasi pertahanan sosial.
Rasa malu dalam konteks Nyambungan jauh melampaui perasaan pribadi, kadang terasa seperti hukuman sosial yang paling ditakuti dalam masyarakat Sunda yang erat. Bagi kaum papa, menghindari label "teu mulang tarima" (tidak tahu membalas budi) adalah perjuangan menjaga harga diri (citarasa) yang sering kali dianggap lebih berharga daripada kekayaan materi. Menolak atau memberikan sumbangan yang terlalu kecil dapat memicu gegeran (gunjingan) yang menyebar cepat, secara efektif mengucilkan individu atau keluarga dari jaringan sosial yang esensial. Mereka yang dicap tidak loyal atau tidak tahu membalas jasa akan kehilangan hak istimewa untuk meminta bantuan di masa depan sebuah kerugian strategis yang bisa fatal saat terjadi musibah atau gagal panen. Oleh karena itu, tindakan ekstrem seperti menggadaikan kain, meskipun menyakitkan secara finansial, adalah cara terakhir yang dilakukan untuk membayar "premi asuransi sosial" agar tetap diterima dalam komunitas.
 Gotong royong itu seperti bambu yang dianyam. Satu helai mudah patah, bersamaan jadi wadah yang kuat menahan beban. Nyambungan semestinya tidak jadi beban sosial.
Gotong royong itu seperti bambu yang dianyam. Satu helai mudah patah, bersamaan jadi wadah yang kuat menahan beban. Nyambungan semestinya tidak jadi beban sosial.
Keengganan menanggung rasa malu ini juga berakar pada keinginan melindungi martabat keluarga di hadapan umum. Ketika seorang anggota keluarga berhajat, kegagalan dalam memenuhi kewajiban Nyambungan dari pihak tamu akan mencoreng nama baik seluruh keturunan. Tekanan ini, yang diturunkan secara turun-temurun, memaksa setiap individu untuk menjaga keseimbangan antara kewajiban kepada keluarga dan kewajiban kepada komunitas. Mereka berkorban bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk memastikan bahwa garis keturunan mereka tetap dianggap sebagai warga nu bener (warga yang benar) yang menjunjung tinggi duduluran (persaudaraan). Ini adalah tindakan heroik dalam kesederhanaan, di mana beban ekonomi ditanggung demi membebaskan diri dari beban psikologis dan sosial yang jauh lebih berat dan berjangka panjang.
Baca Juga: Terjebak Scroll Tanpa Akhir: Bahaya Doomscrolling bagi Mental di Era Digital
Filosofi Mulang Tarima pun terkadang tergeser, dari semangat silih asih (saling mengasihi) menjadi perhitungan témbalan (balasan) yang pragmatis. Niat tulus silih tulungan terbebani oleh ketakutan akan stigma sosial yang dikenal sebagai gegeran (gunjingan) dari tetangga. Untungnya, masyarakat Sunda senantiasa parigel (cerdik dan adaptif). Kesadaran akan beban Nyambungan mulai mendorong perubahan di era kiwari (sekarang).
- Pamisahan Acara: Banyak keluarga memilih untuk mengadakan dua jenis hajatan. Pertama, akad nikah yang sangat privat, berfokus pada keluarga inti dan diwarnai Mulang Tarima hanya dengan kerabat terdekat. Kedua, resepsi yang lebih terbuka untuk umum, di mana Mulang Tarima menjadi sukarela, tidak lagi dicatat.
- Mengutamakan Gawé: Semangat silih tulungan ditegaskan ulang. Masyarakat didorong untuk Mulang Tarima tidak hanya dengan harta (harta), tetapi juga dengan tenaga (gawé). Bantuan berupa memasak, mendekorasi (mapaes), atau mengurus logistik dinilai setara dan jauh lebih meringankan beban Sohibul Hajat daripada sekadar amplop.
- Digitalisasi: Di wilayah urban, beberapa generasi muda mulai menerapkan Nyambungan secara digital melalui transfer bank atau QRIS. Meskipun modern, esensinya tetap Mulang Tarima namun dilakukan tanpa interaksi tatap muka yang dapat menimbulkan tekanan sosial, menjadikan prosesnya lebih privat dan terbebas dari mata pencatat utang sosial.
Mulang Tarima dan Nyambungan akan terus menjadi bagian dari identitas Sunda. Perubahannya menunjukkan kedewasaan budaya dalam mencari keseimbangan. Tujuannya tetap sama: agar duduluran tetap rajeun (akrab) dan gotong royong tetap menjadi sumanget (semangat) hidup, namun tanpa harus mengorbankan harga diri kaum yang kurang mampu.
Baca Juga: Tidak Kompatibel dengan Windows 11? Ini 3 Pilihan Terbaiknya Sebelum 31 Desember 2025
Kemunculan tradisi Nyambungan sebagai kewajiban sosial yang ketat di era 80-an dan 90-an secara tidak langsung menciptakan peluang pasar bagi layanan keuangan non-formal. Ketika seorang Sohibul Hajat atau warga yang harus nyambungkeun mendadak membutuhkan uang tunai untuk menutupi selisih sumbangan atau biaya acara, lembaga keuangan resmi seperti bank terasa terlalu lambat dan rumit. Di sinilah Kosipa (Koperasi Simpan Pinjam) dan, yang lebih dominan, rentenir (bank emok atau lintah darat) bermunculan sebagai "jalan pintas". Mereka menawarkan dana segar dalam hitungan jam tanpa perlu agunan rumit. Bagi masyarakat yang terdesak waktu, bunga mencekik yang ditawarkan rentenir terasa lebih kecil risikonya dibandingkan risiko sosial dicap teu mulang tarima (tidak tahu membalas budi), sehingga menjadi pilihan pahit untuk menutup kebutuhan Nyambungan yang mendesak.
Fenomena ini kian memperparah siklus kemiskinan dan utang sosial. Dana segar yang didapatkan dari Kosipa atau rentenir hanya bersifat sementara, seringkali justru digunakan untuk menutupi kewajiban Nyambungan yang bersifat konsumtif, bukan produktif. Ketika hajatan usai dan tekanan sosial mereda, warga dihadapkan pada kenyataan pahit: mereka kini memiliki utang berbunga tinggi yang harus dibayar mingguan atau bulanan. Ini menciptakan spiral utang baru. Mereka yang tadinya menggadaikan kain untuk membayar utang sosial, kini harus bekerja keras melunasi utang uang yang berbunga, mengubah esensi rereongan dari gotong royong menjadi beban ganda utang material dan sosial yang mengikat kehidupan masyarakat pedesaan selama bertahun-tahun.
Di era kiwari, buku panambih yang dulu usang dan penuh coretan di desa-desa kini mulai tergantikan oleh layar ponsel. Mulang Tarima bertransformasi menjadi Nyambungan Digital. Anak-anak muda Sunda yang berdomisili di kota-kota besar memilih menyertakan kode QRIS atau nomor rekening di undangan, sebuah solusi pragmatis yang memotong rantai tekanan sosial. Transfer dana yang dilakukan dari jauh atau melalui aplikasi, menjadikan Mulang Tarima lebih privat dan terbebas dari tatapan mata tetangga yang mengukur besar kecilnya sumbangan. Dengan cara ini, mereka tetap menunaikan pamali (pantangan) untuk tidak teu mulang tarima, namun tanpa harus menciptakan beban "utang budi" yang kasat mata bagi penerimanya, sekaligus menghormati tradisi dengan cara yang sesuai zaman.
Baca Juga: Persib Bandung Tanpa Empat Pemain Utama Hadapi Madura United, Mampukah Bangkit Usai Tumbang di Asia?
Pergeseran ini membawa masyarakat kembali merenungkan inti filosofi Mulang Tarima. Di banyak hajatan yang lebih kontemporer, penekanan kini bergeser dari "berapa yang harus dibayar" menjadi "bagaimana cara berpartisipasi". Pemberian suvenir dengan pesan yang menyentuh seperti, "Doa Restu Anda adalah panyecep (pemberian) terbaik kami," menjadi semacam penolakan halus terhadap kewajiban balas budi yang kaku. Hal ini adalah upaya untuk membebaskan Mulang Tarima dari hitungan untung-rugi. Sumbangan, baik berupa uang tunai, transfer, atau sekadar kehadiran dan tenaga, kembali dimaknai sebagai wujud tulus silih asih, silih asah, silih asuh semangat untuk saling mengasihi dan menguatkan, bukan lagi sekadar pelunasan utang masa lalu.
Nyambungan dan semangat Mulang Tarima membuktikan sifatnya yang langgeng, mampu menyesuaikan diri dengan goncangan zaman. Mereka yang dulunya terpaksa menggadaikan kain di tengah keterbatasan kini setidaknya memiliki pilihan yang lebih manusiawi dan bermartabat untuk menunjukkan penghormatan. Tradisi gotong royong Sunda terus hidup, tidak mati ditelan modernitas, melainkan beradaptasi menjadi lebih lentur, lebih personal, dan yang terpenting, menjamin bahwa tali silaturahmi tetap terjalin erat, meski amplop kertas kini telah berganti menjadi notifikasi di gawai.