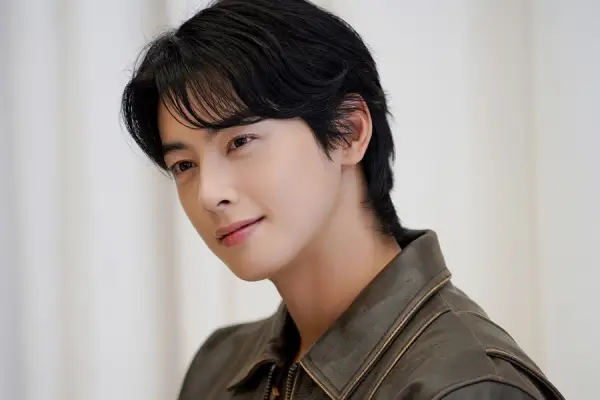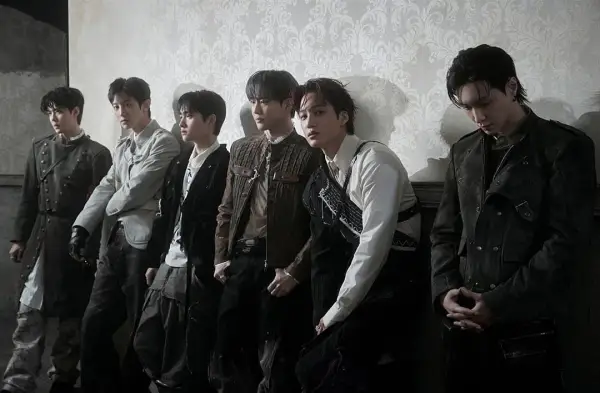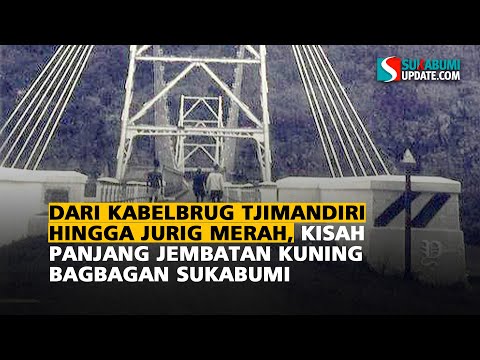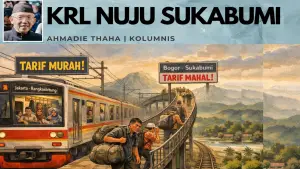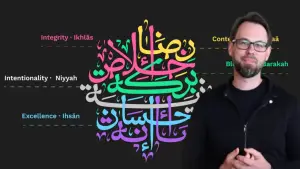SUKABUMIUPDATE.com - Di tengah riuh rendah permainan dan tawa riang, anak-anak Sunda zaman dulu sering menyanyikan paparikan. Saya, dan mungkin Anda, tumbuh dengan melodi-melodi ini tanpa sepenuhnya mengerti makna yang terkandung di dalamnya. Lagu-lagu ini mengalun, menjadi benih kearifan lokal yang tertanam tanpa disadari.
Salah satu syair ini ncukup populer dan mungkin sering Anda lantunkan saat iseng, berbunyi "Trang-trang kolentrang / Si londok paeh nundutan / Tikusruk kana durukan / Mesat gobang kabuyutan." Dan bila masih ada anak-anak yang melantunkannya kembali dan menggema, mereka pastinya anak-anak yang masih hidup bersama kearifan lokal di daerahnya masing-masing di wilayah Priangan.
Namun, Paparikan ini bukan sekadar nostalgia bila kita kaji lebih dalam, melainkan sindiran tajam dari leluhur Sunda untuk kita, sebuah cermin yang menyingkap ironi manusia yang baru sadar setelah terjatuh atau bahkan telah jelas terancam bahaya.
Baca Juga: 22 Sisindiran Basa Sunda, Keindahan dan Kelucuan yang Tersirat dalam Kata
Cermin yang Menyentak di Setiap Bait-nya
Di setiap era, bila mau jujur! Manusia terjebak dalam kesombongan dan kelalaian, yang berujung pada penyesalan. Paparikan ini adalah kritik abadi yang berlaku dari masa lalu, kini, hingga masa depan.
- "Trang-trang kolentrang": Ini adalah onomatope dari bunyi bising dan gemerincing. Di masa lalu, ini bisa jadi suara pertempuran atau riuh rendah kekuasaan. Di masa kini, ia adalah bunyi notifikasi transfer atau validasi media sosial. Ia melambangkan ilusi kesuksesan yang sering membuat kita lengah.
- "Si londok paeh nundutan": Secara harfiah berarti "landak yang mati tertidur." Landak dikenal memiliki pertahanan diri yang kuat dengan duri-nya, namun ia digambarkan mati karena kelengahannya sendiri. Ini metafora untuk manusia yang terlalu nyaman dengan kekuasaannya, statusnya, atau harta bendanya, hingga ia terbuai dan abai pada bahaya.
- "Tikusruk kana durukan": Frasa ini bukan sekadar jatuh, melainkan terjerumus ke dalam kobaran api yang membakar. Ini adalah konsekuensi pahit dari kelalaian. Di masa lalu, ini bisa jadi kejatuhan kekuasaan atau kehancuran. Di masa kini, ini bisa dianalogikan dengan tumpukan utang, kegagalan besar, atau kehancuran mental yang disebabkan oleh ambisi tanpa batas.
- "Mesat gobang kabuyutan": Inilah paradoks paling menyentak. "Kabuyutan" berarti tempat suci atau sumber kearifan leluhur. "Gobang" yang ditarik secara terburu-buru adalah lambang kepanikan. Frasa ini menggambarkan ironi manusia yang baru mencari kebijaksanaan leluhur setelah semuanya hancur. Nilai-nilai luhur hanya dijadikan tameng saat terdesak, bukan sebagai pedoman hidup. Ini adalah kritik pedas bahwa kita sering terlambat mengambil pelajaran dari masa lalu.
Baca Juga: 100 Paribasa Sunda dan Artinya, Papatah Kolot: Ulah Elmu Ajug, Nu Lain Kudu Dilainkeun
Analisis Singkat Filsafat dan Linguistik
Secara filosofis, paparikan ini mengajarkan prinsip karma dan kausalitas. Setiap tindakan, baik disengaja atau tidak, akan memiliki konsekuensi. Kematian landak dan kejatuhannya ke dalam api yang berkobar adalah akibat langsung dari kelalaian. Hal ini mencerminkan pemahaman leluhur Sunda tentang pentingnya kesadaran diri dan kehati-hatian sebagai fondasi kehidupan yang bijaksana.
Secara linguistik, paparikan ini menggunakan gaya bahasa sindiran yang kuat melalui metafora dan personifikasi. Secara linguistik, paparikan ini adalah contoh cerdas dari sastra lisan Sunda yang menggunakan teknik bahasa halus untuk menyampaikan kritik tajam. Alih-alih berbicara terus terang, paparikan ini memanfaatkan metafora yang kuat, seperti "si londok" (landak) yang mewakili manusia sombong dan "durukan" (kobaran api) sebagai konsekuensi fatal, menciptakan gambaran yang jelas tanpa perlu penjelasan panjang.
Melalui personifikasi, paparikan ini memberikan sifat manusia yakni kelalaian dan kesombongan kepada hewan, membuat pesan terasa lebih personal dan universal. Keseluruhan struktur paparikan, yang tergolong dalam genre sisindiran, juga menegaskan fungsinya sebagai sindiran, di mana makna sesungguhnya tersembunyi di balik sampiran yang berima, mengajak pendengarnya untuk merenung dan mencari pesan tersirat yang "dekat" ("parek") dengan realitas hidup mereka.
Penggunaan onomatope, seperti "Trang-trang kolntrang," juga efektif dalam membangun suasana dan pesan yang kuat. "Paparikan" sendiri berasal dari kata "parek" yang berarti "dekat," merujuk pada kedekatan bunyi dan makna yang seringkali tersirat, tidak langsung. (Contoh yang menggunakan kata 'parek': Parek ka leuweung, parek ka cai, parek ka maneh, teu bisa hayang) Interpretasi tentang "londok" sebagai bunglon (chameleon) menambahkan lapisan makna yang sangat dalam dan valid pada paparikan ini.
Dalam beberapa dialek atau konteks, "londok" memang bisa merujuk pada bunglon, bukan hanya landak. Ambiguitas ini justru memperkaya makna dari paparikan tersebut. Mari kita gabungkan ke dalam analisis.
Baca Juga: Wargi Sunda Tahu Si Cepot? Yuk Simak, Pepeling Legend Pewayangan Sunda!
Reinterpretasi "Si Londok": Antara Landak dan Bunglon
Analisis awal, kita mengaitkan "si londok" dengan landak (porcupine), menggunakan durinya sebagai metafora kesombongan dan pertahanan diri yang semu. Namun, interpretasi ada yang mengarah pada bunglon (chameleon) membuka dimensi filosofis yang sama kuatnya, bahkan mungkin lebih relevan dengan sifat manusia yang bermacam-macam. Jika "londok" adalah bunglon, maka makna yang terkandung menjadi:
- Sifat Bunglon: Sifat utama bunglon adalah kemampuannya mengubah warna kulit untuk beradaptasi dengan lingkungan atau menyembunyikan diri. Ini menjadi metafora bagi manusia yang terus-menerus mengubah jati diri, kepribadian, atau prinsip mereka demi kepentingan pribadi, validasi sosial, atau sekadar bertahan hidup.
- Makna "Pah Nundutan": Jika bunglon adalah sosok yang selalu berubah, maka "mati tertidur" bukanlah kematian fisik, melainkan kematian moral atau spiritual. Ini menggambarkan orang yang terlalu sering mengubah "warna" dirinya, hingga akhirnya ia kehilangan identitas aslinya. Ia menjadi "kosong" atau "mati" secara batiniah, meskipun secara fisik masih hidup dan berfungsi layaknya orang lain yang "tertidur."
Dengan interpretasi ini, sindiran dalam paparikan menjadi lebih tajam. Pesannya bukan hanya tentang kesombongan, tetapi juga tentang duplikasi, kemunafikan, dan pengkhianatan terhadap diri sendiri. Orang yang tidak memiliki pendirian teguh, yang terus-menerus berubah demi keuntungan, pada akhirnya akan kehilangan esensi kemanusiaannya.
Pada akhirnya, keindahan puisi tradisional seperti paparikan ini terletak pada kekayaan maknanya. Baik diartikan sebagai landak yang sombong atau bunglon yang tidak berpendirian atau munafik, "si londok" tetap menjadi cerminan sempurna bagi kelemahan manusia yang berlaku di setiap zaman.
 Jika bunglon adalah sosok yang selalu berubah, maka "mati tertidur" bukanlah kematian fisik, melainkan kematian moral atau spiritual.#MaknaHidup #Sastralisan ( Gambar iluistrasi anak desa di Priangan: Chat GPt)
Jika bunglon adalah sosok yang selalu berubah, maka "mati tertidur" bukanlah kematian fisik, melainkan kematian moral atau spiritual.#MaknaHidup #Sastralisan ( Gambar iluistrasi anak desa di Priangan: Chat GPt)
Pesan Abadi: Pengingat untuk Setiap Zaman
Paparikan ini ditutup dengan frasa yang menyentak: "Nyeh prot nyeh prot / Nya nyereh nya kempot." Ini adalah erangan pilu dan gambaran akhir dari mereka yang gagal. Sebuah tangisan atas hidup yang dulu "penuh," kini "kempis" dan kosong. Sebuah gambaran sempurna bagi mereka yang mengejar kesuksesan semu, hanya untuk menyadari bahwa yang mereka dapatkan hanyalah kehampaan.
Pada akhirnya, kita bisa simpulkan bahwa pesan paparikan ini adalah sebuah pengingat abadi yang berlaku di setiap waktu. Ia bukan hanya sekadar puisi, tetapi sebuah kompas moral yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ia mengingatkan kita untuk selalu waspada, rendah hati, dan berpegang pada kearifan, bukan sebagai pilihan terakhir saat kita tenggelam, melainkan sebagai pedoman utama dalam menjalani hidup.
Baca Juga: Sambut 2023, Ini Pepatah Semar Badranaya: Pepeling Tokoh Punakawan Wayang Golek
Berikut adalah beberapa sumber rujukan dan tokoh yang kemungkinan pernah membahas topik serupa, meski mungkin tidak secara eksplisit dengan analisis yang sama persis:
-
Para budayawan dan akademisi Sunda:
-
Prof. Yus Rusyana: Beliau adalah seorang sastrawan dan guru besar sastra Sunda. Karya-karyanya banyak membahas tentang sastra lisan, termasuk paparikan, sisindiran, dan pantun. Analisisnya sering kali mengaitkan sastra dengan nilai-nilai filosofis dan kearifan lokal.
-
Dr. Undang Ahmad Darsa: Seorang ahli sastra Sunda yang sering mengkaji naskah kuno dan kearifan Sunda. Ia mungkin pernah menyinggung makna-makna tersirat dalam paparikan.
-
Dr. Zaini Alif: Beliau adalah pendiri Komunitas Hong yang fokus pada pelestarian permainan tradisional anak-anak, termasuk paparikan. Ia sering memberikan konteks filosofis di balik permainan dan lagu-lagu anak.
-
-
Jurnal akademik dan penelitian:
-
Anda bisa mencari jurnal-jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh perguruan tinggi di Jawa Barat, seperti Universitas Padjadjaran (Unpad) atau Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). Kata kunci yang relevan untuk dicari adalah "analisis sisindiran," "paparikan Sunda," "filosofi sastra lisan Sunda," atau "kearifan lokal Sunda."
-
-
Media massa dan komunitas daring:
-
Beberapa artikel di media massa atau blog pribadi yang fokus pada budaya Sunda mungkin pernah membahas topik ini dengan kedalaman analisis bervariasi dan sering kali bersifat populer.
-