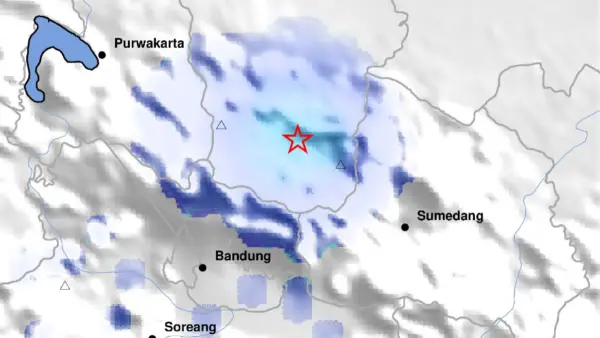Penulis: Farid Gaban
"Tujuan pembangunan (peradaban) adalah memurnikan watak manusia, bukan memperbanyak keinginan (multiplication of wants)," kata EF Schumacher (Small is Beautiful).
Schumacher memperkenalkan istilah "enoughness", kebercukupan, yang diadopsi dari filsafat Buddhisme.
Berkecukupan bukan berarti berkelimpahruahan materi, tapi merasa cukup dan bersyukur dengan apa yang ada. Merasa berlimpahruah bahkan dalam kesederhanaan.
Ini salah satu yang kuat dalam tradisi Jawa dan masyarakat-masyarakat tradisional lain yang sering dianggap tidak suka kompetisi: urip sak madyo (hidup secukupnya).
Itu bukan mentalitas primitif. Di era manajemen modern, Stephen Covey menyebutnya sebagai abundance mentality: keyakinan bahwa selalu ada sumberdaya dan peluang yang cukup bagi semua/setiap orang untuk sukses; dan keyakinan bahwa sukses orang lain tidak menghilangkan potensi sukses diri kita.
Abundance mentality di kalangan masyarakat tradisional Indonesia, menurutku, diilhami oleh kelimpahan sumberdaya alam kita. Sumberdaya alam yang saya maksud adalah keragaman hayati, bukan tambang dan mineral.
Keragaman hayati (flora, fauna, ekosistem) membuat kita merasa berkecukupan, hampir mustahil kelaparan, karena "tongkat kayu dan batu jadi tanaman". Keragaman itu membuat hidup kita lebih longgar, dan karenanya kecil kebutuhan untuk bersaing, sebaliknya justru mendorong kerjasama (gotong royong).
SDA tambang dan mineral, atau perkebunan monokultur seperti sawit, justru mencerminkan scarcity, kelangkaan, hanya segelintir orang yang menikmati hasilnya.
Dari dua kali keliling Indonesia saya menyaksikan konflik sosial yang berkelanjutan dan mengeras di kantong-kantong usaha ekstraktif tambang serta sawit.
Secara umum, semangat gotong royong masih ada dalam masyarakat tradisional kita, terutama di perdesaan dan pedalaman. Tapi, semangat ini makin menyusut.
Pertama, abundance mentality luntur oleh kian rusaknya alam dan menyusutnya keragaman hayati.
Kelestarian alam, hutan dan laut, penting sebagai fondasi tata sosial dan budaya. Itu sebabnya, Bhutan, misalnya, negeri kecil di kaki Himalaya, memilih melestarikan hutan untuk menjamin kohesi sosial yang menjadi fondasi kebahagiaan.
Bhutan adalah negeri yang memperkenalkan Indeks Kebahagiaan Nasional dan mewajibkan pemerintahannya menjaga 70% kelestarian hutan sebagai kewajiban konstitusional.
Kedua, spirit gotong royong berkurang oleh format ekonomi dan kebijakan publik pemerintah yang mengedepankan kompetisi serta memicu ketimpangan.
Pemerintahlah yang merusak spirit gotong royong dan solidaritas sosial.
Gotong royong cuma ada dalam komunitas kecil. Dan bagaimana kita bisa mengatakan harmoni sosial ketika 50% lahan dikuasai oleh 60 keluarga (termasuk keluarga Presiden Prabowo)?
Ketiga, gotong royong juga meluntur ketika program-program charity yang salah arah terus dikedepankan: bansos dan dana transfer desa. Rakyat diberi upah untuk memperbaiki jalan, yang dulu dilakukan dengan gotong royong tanpa bayar. Bantuan sosial (bansos) memicu moral hazard dan bahkan konflik di masyarakat (saling iri), mengajari orang untuk fokus pada uang sebagai ukuran.
Di desa-desa, orang tidak lagi bekerja bersama, mereka kerja sendiri-sendiri, bersaing dalam kemiskinan.
Memang ada kelompok-kelompok, seperti poktan (kelompok tani), tapi petani bekerja sendiri-sendiri setelah mendapat bantuan pemerintah, pada gilirannya memicu konflik dan korupsi, serta lunturnya trust antar-warga.
Swedia mungkin tidak kuat dalam gotong royong masyarakat seperti Indonesia atau Bhutan. Tapi, seperti negara-negara Skandinavia lain, spirit gotong royong dicerminkan dalam usaha koperasi serta kebijakan publik yang mendahulukan pemerataan.
Renungan di atas bisa mengilhami arah pembangunan kita ke depan. Apakah kita akan mendahulukan kelimpahan materi/ekonomi yang merusak alam sebagai fondasi harmoni sosial, atau sebaliknya.
Negara Skandinavia seperti Swedia selalu ada di urutan teratas negara paling bahagia dalam survai Indeks Kebahagiaan yang dilakukan oleg Gannet Poll.
Baca Juga: Ayep Zaki Tak Pernah Temui Massa Demo di Balai Kota Sukabumi, Ternyata Bukan Takut!
Bahkan Bhutan, negeri yang mengusulkan kebahagiaan sebagai ukuran sukses pembangunan, ada di urutan agak bawah.
Bhutan negeri yang lebih miskin dari Indonesia dari GNP per capita.
Tapi, apa yang membuat Bhutan dan Skandinavia bisa sama-sama bahagia meski kontras secara ekonomi?
Ada 4 komponen yang konsisten ada dalam parameter kebahagiaan:
Social security. Warga merasa aman, tidak takut miskin. Skandinavia lewat kemakmuran yg disalurkan lewat welfare state. Bhutan lewat harmoni/solidaritas sosial; miskin tapi ada social safety net dalam masyarakat/keluarga.
Kohesi sosial. Solidaritas dalam masyarakat yang sama-sama peduli tentang kepentingan bersama (publik). Di Skandinavia tecermin dalam konsep koperasi.
Good governance. Pemerintah yang amanah dan akuntabel, yang terus-menerus meningkatkan kualitas kebijakan publik, serta mendorong pemerataan bersama; egaliter; menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Bhutan, yang dulu berbentuk monarki belakangan berubah menjadi republik, dengan watak kepemimpinan yang egaliter.
Kelestarian alam. Baik Bhutan maupun Skandinavia dicirikan oleh keindahan dan kelestarian alam yang menjadi sumber kebahagiaan dan kekayaan spiritualitas. Alam yang rusak, banjir, longsor dan polusi, adalah sumber kesedihan.
Catatan untuk Indonesia
Baik Skandinavia maupun Bhutan adalah negara-negara kecil, apakah Indonesia tidak terlalu besar jika ingin mencoba menerapkan kebijakan serupa?
Ukuran negara menunjukkan pentingnya otokomi daerah yang genuine, kalau perlu bahkan federasi.
Setiap kabupaten atau provinsi tak bisa beralasan terlalu besar untuk bisa seperti Bhutan atau Skandinavia dalam menjaga alam, mendorong pemerataan, meningkatkan kualitas pemerintahan dan memastikan jaminan serta kohesi sosial.*