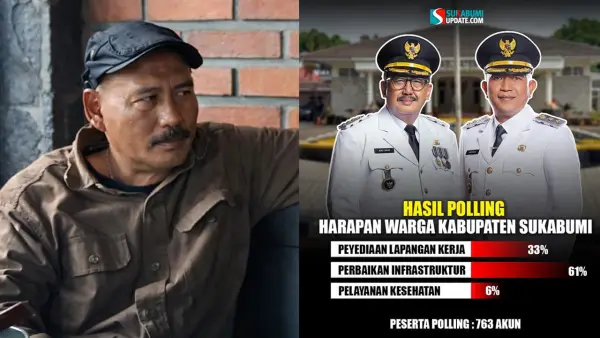Penulis : Cak AT – Ahmadie Thaha
Ini kisah Peter Gould, desiner muslim yang mempengaruhi produk-produk Apple. Sebelum kita cepat mengira ini sekadar kisah spiritual seorang mualaf Barat yang “menemukan kedamaian”, ada baiknya kita menaruh satu batu pijakan: Peter Gould bukan orang pinggiran di dunia desain digital.
Ia desainer profesional, pendiri studio kreatif, penulis tentang metodologi desain, dan pengajar yang masuk ke ruang-ruang yang biasanya hanya ditempati oleh para insinyur, product manager, dan arsitek pengalaman pengguna perusahaan teknologi besar.
Ia berbicara di hadapan desainer Google, Apple, dan korporasi global lain— bukan sebagai penceramah agama, melainkan sebagai orang yang paham bahasa produk, antarmuka, sistem, dan algoritma. Kerangka desainnya, yang tertuang dalam bukunya _The Heart of Design_, menjadi rujukan mereka.
Ia bukan sekadar “orang saleh yang kebetulan bisa desain”, melainkan praktisi yang berada di jantung ekosistem digital modern. Itu sebabnya, ketika ia bicara tentang iman, desain, dan teknologi, yang sedang kita dengar bukan romantisme spiritual, melainkan intervensi etis ke dalam mesin peradaban digital.
Peter Gould tidak lahir dari panggung-panggung dakwah, tidak dibesarkan di serambi masjid, apalagi di lorong-lorong kitab kuning. Ia lahir di pinggiran Sydney, dari keluarga kulit putih kelas menengah yang — kalau boleh meminjam istilah sosiolog — hidup rapi, aman, dan agak alergi pada hal-hal yang berbau “Tuhan”.
Baca Juga: Rhenald Kasali: Bisnis 2026 Digerakkan AI, Emosi Publik dan Generasi yang Menolak Kantor
Di Australia, agama sering diperlakukan seperti benda antik: disimpan, dihormati secara sopan, tetapi tidak disentuh. Peter pun tumbuh tanpa beban iman, tanpa kegelisahan metafisik, tanpa dorongan untuk mencari langit. Tuhan baginya kala itu sekadar artefak kebudayaan, semacam foto hitam-putih di museum peradaban.
Sampai suatu hari, seperti dalam banyak kisah besar yang selalu berawal dari hal remeh, ia berjumpa sebuah keluarga Muslim yang tinggal di dekat rumahnya. Bukan ceramah, bukan debat teologi, bukan pula poster-poster ayat di tembok.
Hanya pergaulan, percakapan, dan rasa ingin tahu yang mula-mula sekadar iseng: apa itu Islam? Siapa Muslim? Mengapa mereka hidup dengan cara yang terasa asing namun tenang? Dari rasa ingin tahu itu, terbuka sebuah semesta yang belum pernah ia jejaki: dunia spiritual yang tidak sentimental, tetapi juga tidak kering. Dunia yang tidak ribet, tetapi terasa dalam.
Pada usia 18, 19, 20 tahun — usia ketika kebanyakan anak muda sibuk mencari jati diri di kafe, konser, atau lembar-lembar kontrak magang — Peter justru mulai menelusuri pertanyaan yang jarang disentuh generasinya: siapa Pencipta? Apa arti hidup?
Ia membaca, bertemu orang-orang dari berbagai latar, mengalami perjumpaan yang tak ia rencanakan. Setahun lebih ia mengendap dalam pencarian itu. Hingga pada usia 20, ia memutuskan memeluk Islam.
Keputusannya bukan ledakan emosi. Ia bahkan mengakui tak langsung memahami semuanya. Tetapi pada tingkat intelektual, ia menemukan sesuatu yang — menurut pengakuannya — jernih dan tidak berbelit: ada Allah sebagai Pencipta, ada makhluk sebagai ciptaan. Selesai. Tidak beranak-pinak. Tidak perlu labirin metafisika.
Namun di balik kejernihan kepala itu, ada yang lebih menentukan: gerak di dalam hati. Sebuah keyakinan yang tak berisik, bahwa hidup ini terhubung pada sesuatu yang lebih besar, bahwa kehadiran Ilahi tidak jauh di atas awan, melainkan dekat, meliputi, dan senyap mengalir dalam keseharian.
Seorang gurunya pernah memberi perumpamaan yang sederhana sekaligus mematikan kesombongan intelektual: iman itu seperti madu. Kita bisa berbicara tentang madu, meneliti kandungannya, membaca artikel ilmiahnya, menghafal definisinya di Wikipedia.
Baca Juga: Fahri Hamzah di BP3R: Mandat Hashim untuk Gempur Monopoli Properti dan Hidupkan Pengembang Daerah
Tetapi sampai kita benar-benar mencicipinya, kita tidak pernah tahu apa itu madu. Islam, bagi Peter, bukan sekadar konsep yang “masuk akal”. Ia adalah rasa yang dialami.
Namun, kisahnya tidak berhenti pada pengalaman batin. Peter adalah desainer. Sejak muda ia akrab dengan gambar, sketsa, dan dunia visual. Ia hidup di masa ketika komputer mulai menjadi kanvas baru, ketika Photoshop, HTML, dan perangkat digital membuka kemungkinan-kemungkinan yang belum pernah ada.
Maka pertemuannya dengan Islam bukan sekadar pertemuan iman, melainkan juga pertemuan estetika. Ia tersentak oleh keindahan masjid, oleh harmoni ruang, cahaya, kaligrafi, dan geometri.
Di sebuah masjid bergaya arsitektur Turki di Sydney, ia merasa seolah dipindahkan ke Bosphorus tanpa paspor. Keindahan itu bukan sekadar dekorasi, melainkan pengalaman: ruang yang mengajak diam, menunduk, dan mengingat.
Dari situ, lahirlah keputusan yang terdengar sederhana tetapi berani: ia mengumpulkan uang dari pekerjaan lepasnya, lalu menghabiskannya untuk berjalan. “Earn, travel, repeat,” demikian ritme hidupnya.
Ia berangkat ke Maroko, Suriah, Turki, Yordania, Malaysia, Indonesia, Makkah, Madinah, bahkan hingga Beijing, mengunjungi masjid-masjid tua yang berdiri seperti saksi bisu perjalanan panjang peradaban Islam.
Ia tidak sekadar berwisata; ia mengamati, menyerap, dan bertanya: mengapa Islam di satu tempat tampak berbeda dengan di tempat lain, tetapi ruhnya terasa sama?
Seorang gurunya memberi kunci yang kelak menjadi poros pemikirannya: Islam itu seperti air jernih. Di mana pun ia mengalir, ia memantulkan warna tanah yang dilewatinya.
Di Tiongkok, masjid tampak Tionghoa. Di Turki, ia menjelma kubah-kubah agung. Di Nusantara, ia menyatu dengan kayu, atap tumpang, dan suara azan yang bersahabat dengan gamelan. Islam tidak kehilangan kemurniannya justru karena ia tidak memaksakan satu rupa.
Dari perjalanan itu, Peter sampai pada sebuah kesimpulan yang — bagi banyak orang — terasa sederhana, tetapi implikasinya radikal: tidak ada yang namanya Islam tunggal dalam ekspresi budaya. Yang ada adalah satu iman, tetapi banyak wajah.
Islam bukan barang impor yang harus selalu dikemas dengan ornamen Arab. Ia adalah makna yang menjelma dalam konteks. Ia adalah air yang tetap jernih meski melewati tanah yang berbeda-beda.
Di titik inilah kisah Peter Gould menjadi lebih dari sekadar kisah seorang mualaf Barat yang menemukan “ketenangan”. Ia adalah kisah tentang bagaimana iman, ketika benar-benar dipahami sebagai madu dan bukan sekadar definisi, mendorong seseorang melampaui dirinya sendiri: dari pencarian personal menuju pembacaan peradaban. Dari rasa di hati menuju pertanyaan tentang bentuk di dunia.
Maka, ketika ia bertanya, “Jika Islam di Cina tampak Cina, lalu bagaimana Islam di zaman digital seharusnya tampak?”, sesungguhnya ia sedang mengajukan pertanyaan yang juga relevan bagi kita di Indonesia: apakah kita hanya sibuk mewarisi simbol, atau berani menafsirkan makna? Apakah kita puas dengan kemasan, atau bersedia mengecap madu itu hingga ke dasar lidah?
Seri ini baru permulaan. Di bagian berikutnya, kita akan mengikuti bagaimana air jernih yang ditemukannya di masjid-masjid dunia itu, kelak dibawanya ke ruang-ruang yang paling tak terduga: meja desain teknologi, korporasi global, dan dunia yang lebih sibuk menghitung klik daripada mengingat Tuhan.
Ma'had Tadabbur al-Qur'an, 17/1/2026