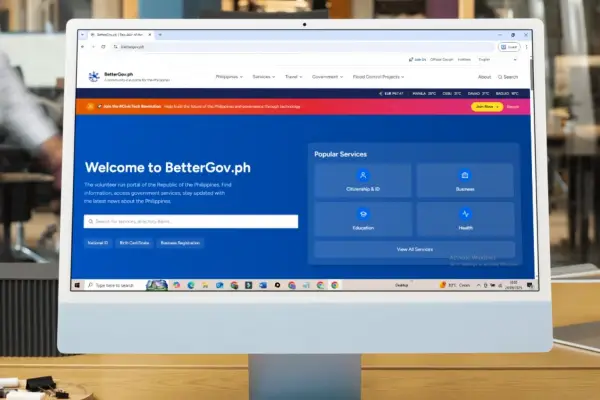SUKABUMIUPDATE.com - Ada sebuah kutipan yang telah membumi, kutipan yang paling relevan dan sering dikutip secara global, yang secara lugas menjelaskan betapa sulitnya memberantas korupsi, kata-kata ini berasal dari sejarawan dan politikus Inggris, Lord Acton, yang menyoroti sifat inheren kekuasaan itu sendiri, berbunyi:
"Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely." (Kekuasaan cenderung merusak, dan kekuasaan absolut merusak secara absolut.)
Kutipan ini sangat relevan karena menjelaskan kesulitan pemberantasan korupsi dari akarnya, apa lagi jika bukan struktur kekuasaan, karena: Kekuasaan Cenderung Merusak (Power Tends to Corrupt): Bahwa setiap individu yang memegang kekuasaan (baik dalam politik, birokrasi, maupun korporasi) memiliki kecenderungan psikologis untuk menyalahgunakan wewenang tersebut demi keuntungan pribadi atau kelompok. Korupsi adalah manifestasi dari penyalahgunaan wewenang ini. Kekuasaan Absolut Merusak Secara Absolut (Absolute Power Corrupts Absolutely): mengapa korupsi sulit dibasmi karena ia tumbuh subur di tempat kontrol dan pengawasan menghilang. Ketika kekuasaan tidak dibatasi (unchecked), pemegang kekuasaan dapat menciptakan sistem dan hukum untuk melindungi dirinya sendiri dari penuntutan (impunitas), sehingga upaya pemberantasan menjadi sia-sia.
Atau, masih ingat dengan kutipan ini?
"Corruption is, quite simply, stealing from the poor." (Korupsi adalah, sederhananya, mencuri dari orang miskin.)
Kesulitan memberantas korupsi juga muncul karena korupsi seringkali tersembunyi di balik proyek-proyek besar, padahal dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat miskin yang kehilangan hak atas layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Korupsi sulit dibasmi karena ia tidak terlihat sebagai kejahatan kekerasan, tetapi dampaknya adalah merampas kehidupan rakyat paling rentan.
Baca Juga: Bapenda Sukabumi Serahkan SK PPPK Paruh Waktu, Tekankan Penguatan Pelayanan Publik
Dan setiap 9 Desember, kalender nasional kita menandai Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia), seharusnya menjadi hari di mana kita sebagai bangsa yang berdaulat merayakan kemajuan dalam memerangi musuh terbesar pembangunan: korupsi. Namun, realitas di lapangan seringkali terasa kontradiktif. Hari ini, perayaan tersebut lebih menyerupai sebuah pengingat yang menyakitkan bahwa praktik kotor ini masih menjadi bayang-bayang gelap, merayap dan mengakar dalam setiap sendi kehidupan publik. Korupsi bukan sekadar kejahatan kerah putih, melainkan sebuah pengkhianatan terhadap cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat, merampas hak-hak dasar yang seharusnya dinikmati oleh masyarakat luas.
Peringatan Hakordia tahun ini, dengan tema sentral "Satukan Aksi, Basmi Korupsi!", menuntut kita untuk berhenti sejenak dari sekadar retorika dan mulai mengevaluasi secara jujur. Mengapa setelah puluhan tahun reformasi dan penegakan hukum yang intensif, kejahatan ini justru terasa semakin canggih dan terstruktur? Mengapa jerat gurita korupsi ini begitu kuat, membelit institusi seperti simpul mati yang sulit diurai? Untuk memahami ini, kita harus menyelam lebih dalam ke dalam tiga dimensi masalah: sistem, budaya, dan moralitas yang saling bersimbiosis membiakkan praktik koruptif.
Tanggal 9 Desember, diperingati sebagai Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia), seharusnya menjadi momen refleksi kolektif. Namun, alih-alih merayakan kemenangan, kita dihadapkan pada realitas getir: korupsi di Indonesia masih merajalela, melilit institusi seperti tentakel gurita yang sulit dilepaskan. Fenomena ini bukan sekadar kejahatan transaksional, melainkan sebuah penyakit sistemik yang mengancam fondasi demokrasi dan pembangunan.
Baca Juga: Energi Klasik Andromedha, Diskografi dan 'Emosi' yang Membara di JogjaROCKarta 2025
Mengapa slogan "Satukan Aksi, Basmi Korupsi!" yang diusung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terasa begitu mendesak? Karena upaya pemberantasan kini menghadapi tembok besar yang terdiri dari dua elemen utama: kerentanan sistem dan kelemahan moralitas individu.
- Keroposnya Dinding Sistematis (Opportunity)
Penyakit korupsi bersemi subur dalam birokrasi yang didominasi oleh ketidaktransparanan. Ketika proses perizinan, pengadaan barang dan jasa, hingga alokasi dana publik tidak dibuka secara gamblang kepada publik, ruang bagi penyimpangan menjadi tak terbatas.
- Birokrasi Abu-abu: Proses pengambilan keputusan yang kompleks dan manual memberikan kesempatan pejabat untuk meminta 'pelicin' demi mempercepat urusan. Minimnya digitalisasi dan intervensi manusia yang tinggi adalah musuh transparansi.
- Biaya Politik Mahal: Sistem demokrasi yang menuntut biaya besar untuk kampanye dan mempertahankan kekuasaan memaksa para pejabat terpilih mencari modal balik. Dana publik seringkali menjadi sasaran utama untuk 'mengembalikan investasi' ini, menciptakan lingkaran setan korupsi politik.
- Lemahnya Pengawasan: Struktur pengawasan internal (Inspektorat Jenderal) seringkali tunduk pada eksekutif, sementara lembaga pengawasan eksternal (seperti DPR dan BPK) memiliki keterbatasan atau, yang lebih parah, turut menjadi bagian dari praktik kolusif.
- Erosi Moralitas dan Budaya Permisif (Rationalization)
Korupsi telah bertransformasi dari tindakan kriminal menjadi 'kebiasaan' yang diterima secara sosial di beberapa lingkaran. Ketika pejabat publik hidup dalam kemewahan yang tidak sesuai dengan pendapatan resmi mereka, namun masyarakat tetap mengagumi dan menghormati, maka standar moralitas telah bergeser.
- Budaya Patronase: Loyalitas kepada atasan atau kelompok seringkali lebih diutamakan daripada loyalitas kepada negara dan konstitusi. Penempatan jabatan didasarkan pada kedekatan (nepotisme) alih-alih pada meritokrasi atau kemampuan.
- Keserakahan Individu (Greed): Mengacu pada teori Fraud Triangle , di mana korupsi dipicu oleh kesempatan, tekanan, dan rasionalisasi, faktor keserakahan (greed) tetap menjadi pemicu utama. Kekayaan seakan tidak pernah cukup, didorong oleh tekanan gaya hidup konsumtif yang dipamerkan di ruang publik.
Baca Juga: Bos BP BUMN Ungkap Jalur KRL Akan Diperpanjang hingga Sukabumi dan Cikampek
Meskipun Indonesia memiliki lembaga antikorupsi yang diakui, upaya pemberantasan kerap terganjal oleh tantangan penegakan hukum yang menghasilkan impunitas.
- Hukuman yang 'Diskriminatif': Seringkali, sanksi yang dijatuhkan kepada koruptor tidak sebanding dengan kerugian negara yang ditimbulkan. Putusan pengadilan yang memberikan hukuman ringan, bahkan pembebasan, mengirimkan sinyal berbahaya: bahwa risiko korupsi lebih rendah daripada potensi keuntungannya.
- Intervensi Kekuasaan: Lembaga penegak hukum, termasuk KPK, seringkali menghadapi upaya pelemahan melalui revisi undang-undang atau intervensi politik, yang merusak independensi dan efektivitas kerja mereka.
Kondisi ini menciptakan persepsi ketidakadilan di mata masyarakat. Ketika rakyat kecil dihukum berat atas pencurian receh, sementara pejabat yang merampok triliunan mendapat fasilitas dan diskon hukuman, maka kepercayaan publik terhadap negara dan hukum akan runtuh, yang pada akhirnya melemahkan legitimasi pemerintah.
Pragmatisme memiliki kaitan yang sangat erat dan signifikan dengan fenomena korupsi yang menggurita. Dalam konteks ini, pragmatisme tidak merujuk pada aliran filsafat secara umum, melainkan pada pemahaman praktis yang cenderung mengedepankan hasil atau keuntungan nyata (utilitas) di atas pertimbangan etika, moral, atau prosedur yang benar.
Baca Juga: HP Harga Realistis Performa Sadis Itu Infinix Hot 60 Pro
Pragmatisme Sebagai Pembenar Aksi Koruptif
Pragmatisme, dalam konteks sosial dan politik Indonesia, seringkali dimanifestasikan sebagai sikap "pokoknya beres dan untung," tanpa peduli cara. Ini menjadi pintu gerbang utama yang merasionalisasi tindakan korupsi.
- Politik Pragmatis (The Means Justifies The End)
- Target vs. Aturan: Di dunia politik, pragmatisme mewujud dalam pencapaian kekuasaan atau jabatan. Jika untuk memenangkan pemilu atau mendapatkan proyek diperlukan suap (korupsi) atau kolusi, maka tindakan itu dianggap "perlu" dan "efektif." Hasilnya (kekuasaan/proyek) dianggap lebih penting daripada cara yang ilegal.
- Biaya dan Kecepatan: Pejabat atau politisi didorong oleh pragmatisme untuk mencari dana politik (modal balik). Daripada membangun sistem pendanaan yang transparan dan legal, mereka secara pragmatis memilih jalur korupsi karena dinilai lebih cepat, lebih besar, dan lebih terjamin hasilnya.
- Birokrasi Pragmatis (Simplifikasi Prosedur Ilegal)
- Sikap "Mempermudah": Dalam pelayanan publik, jika birokrasi legal terlalu berbelit-belit dan lambat, masyarakat atau pengusaha secara pragmatis akan memilih menyuap (memberi "uang pelicin") agar urusan cepat selesai. Bagi si pemberi, itu adalah investasi untuk efisiensi; bagi si penerima, itu adalah pendapatan tambahan yang cepat. Kedua pihak sama-sama pragmatis dan diuntungkan oleh kelemahan sistem.
- Menghindari Risiko: Pejabat publik yang pragmatis akan membuat keputusan yang "aman" atau menguntungkan kelompoknya, meskipun melanggar etika. Misalnya, memilih vendor yang memberi fee terbesar, dengan asumsi bahwa keuntungan finansial pribadi lebih berharga daripada risiko hukum yang mungkin bisa dinegosiasikan.
- Pragmatisme Sosial (Acceptance)
- Budaya Instan: Masyarakat yang pragmatis cenderung memandang korupsi sebagai hal yang "tidak ideal" tetapi "tidak bisa dihindari" (budaya permisif). Sering muncul pembenaran: "Yang penting pekerjaan selesai," atau "Semua orang juga begitu." Sikap ini melemahkan kontrol sosial dan memungkinkan korupsi tumbuh subur.
- Pergeseran Nilai: Pragmatisme secara efektif menggeser nilai-nilai luhur seperti kejujuran dan integritas menjadi sekadar formalitas. Yang diutamakan adalah keberhasilan material dan finansial, terlepas dari sumbernya.
Baca Juga: Banjir Limpasan Salabintana Bongkar Masalah Tata Ruang: Hutan Menyusut, Kafe Bermunculan
Dengan demikian, pragmatisme menjadi rasionalisasi utama bagi para pelaku korupsi. Itu adalah pemikiran yang membenarkan bahwa tujuan yang dianggap baik (kekayaan, kekuasaan, efisiensi) dapat dicapai dengan cara yang buruk (korupsi).
Untuk membasmi korupsi yang menggurita, aksi tidak bisa hanya berfokus pada penindakan. Perlu adanya pergeseran paradigma, yaitu menjadikan integritas sebagai nafas birokrasi dan budaya bangsa. Oleh karena itu, upaya pemberantasan korupsi harus bergerak dari sekadar penindakan reaktif menjadi pembangunan budaya yang proaktif. Kita harus mengedukasi generasi muda bahwa integritas adalah mata uang sosial tertinggi, dan bahwa ketamakan tidak pernah sebanding dengan kehancuran negara.
Pemerintah harus berani mengebiri sistem politik yang rakus biaya, memberlakukan sanksi pemiskinan yang nyata, dan memastikan bahwa tidak ada satu pun individu, sekuat apa pun jaringannya, yang kebal terhadap jerat hukum. Hanya dengan reformasi total, kita dapat mengganti budaya permisif dengan etos kerja yang jujur.
Pertarungan melawan korupsi adalah pertarungan moral. Hakordia adalah pengingat bahwa masa depan yang adil dan makmur sangat bergantung pada keputusan kita hari ini apakah kita memilih untuk terus membiarkan gurita itu bernapas, atau kita menyatukan seluruh kekuatan sipil dan struktural untuk memotong tentakelnya, selamanya. Momen ini menuntut bukan hanya janji, melainkan komitmen tanpa henti untuk menjadikan transparansi, akuntabilitas, dan integritas sebagai nilai yang tak bisa ditawar, demi mewujudkan mimpi Indonesia yang bersih dan bermartabat.