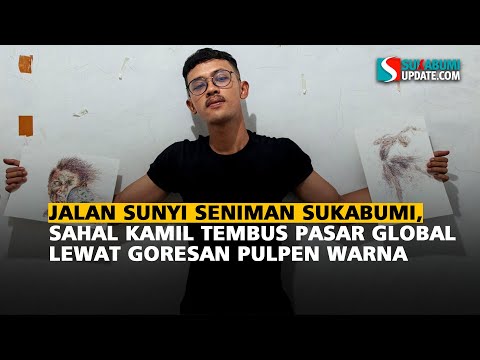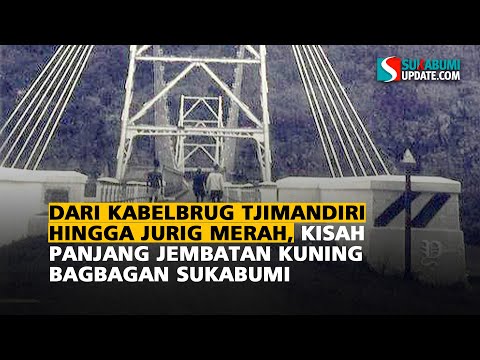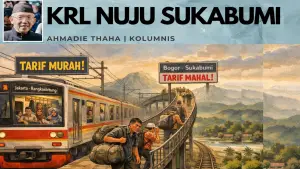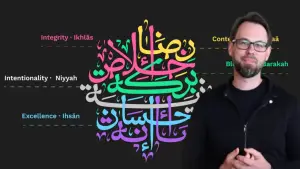Penulis: drh Slamet (Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS/Dapil Jabar IV)
Beberapa waktu terakhir, wilayah Kabupaten Sukabumi kembali diuji dengan rentetan bencana banjir dan longsor. Curah hujan ekstrem mengguyur kawasan selatan Sukabumi secara berturut-turut, mengakibatkan meluapnya sungai-sungai dan rusaknya infrastruktur desa. Puluhan rumah warga terendam lumpur, akses jalan terputus, dan lahan pertanian rusak parah.
Bencana ini bukan yang pertama, dan bukan pula yang terakhir jika kita tidak segera berbenah. Sebagai wakil rakyat di Komisi IV DPR RI yang membidangi urusan lingkungan hidup, kehutanan, dan pertanian, saya merasa berkewajiban untuk menyuarakan bahwa mitigasi bencana bukan sekadar upaya pasca-kejadian, tapi harus dimulai jauh sebelum bencana datang.
Hilirisasi Air dan Daya Dukung Alam yang Menurun
Wilayah Sukabumi memiliki kondisi geografis yang kompleks—pegunungan, perbukitan, dan aliran sungai yang panjang. Tapi jika kawasan hulu semakin rusak oleh alih fungsi lahan, pembalakan liar, dan lemahnya tata kelola ruang, maka banjir bandang akan menjadi tamu langganan setiap musim hujan tiba.
Banyak masyarakat bertanya, "Mengapa banjir dan longsor kini lebih sering terjadi, bahkan di wilayah yang dulu relatif aman?" Jawabannya ada pada kerusakan lingkungan yang sistemik dan berulang. Ketika tutupan hutan di hulu terkikis dan tanah kehilangan daya serapnya, maka air hujan tidak lagi diserap bumi, melainkan langsung mengalir deras ke hilir membawa material lumpur, batu, bahkan pohon tumbang.
Baca Juga: Rawat Masa Depan, Slamet Bawa Sukabumi Jadi Percontohan Rehabilitasi Lahan Lewat Agroforestri
Urgensi Mitigasi Berbasis Komunitas
Mitigasi bencana merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan sinergi dan kolaborasi dari semua pihak — mulai dari pemerintah pusat dan daerah, hingga para pemangku kebijakan dan masyarakat di tingkat desa. Dalam hal ini, peran pemerintah menjadi sangat penting. Dengan kewenangan yang dimiliki serta dukungan anggaran, pemerintah harus mampu menjadi dirigen yang mengorkestrasi keterlibatan semua elemen secara terpadu. Salah satu pendekatan yang terbukti efektif adalah mitigasi berbasis komunitas (community-based disaster risk reduction), yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam upaya pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana.
Langkah-langkah sederhana seperti menanam kembali pohon di kawasan rawan longsor, menjaga sempadan sungai, membangun sistem peringatan dini, hingga simulasi evakuasi warga, semuanya bisa dilakukan dengan pendekatan kolaboratif. Kita harus membangun budaya sadar risiko. Tidak cukup hanya bersimpati saat bencana datang, lalu lupa ketika cuaca kembali cerah.
Kebijakan dan Pengawalan Anggaran yang Tepat Sasaran
Di tingkat pusat, saya terus mendorong agar anggaran dan program-program Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, serta BNPB benar-benar menjangkau wilayah rawan bencana seperti Sukabumi. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis, pembangunan infrastruktur konservasi, hingga edukasi dan pelatihan kebencanaan harus menjadi prioritas.
Saya juga menegaskan bahwa anggaran mitigasi bukanlah biaya, melainkan investasi masa depan. Biaya penanggulangan pasca-bencana selalu jauh lebih besar daripada mencegahnya. Oleh karena itu, tata kelola anggaran harus transparan dan melibatkan warga sebagai subjek, bukan sekadar objek penerima bantuan.
Penutup: Bergerak Bersama, Bukan Menyalahkan
Rentetan bencana ini semestinya menjadi pengingat keras bagi kita semua bahwa alam memiliki batas daya dukung. Jika kita terus mengeksploitasinya tanpa memikirkan keseimbangan, maka alam akan "melawan" dalam bentuk bencana. Namun bukan saatnya saling menyalahkan. Ini saatnya untuk bergerak bersama.
Saya mengajak seluruh pihak—pemerintah, swasta, tokoh masyarakat, lembaga pendidikan, dan tentu saja warga Sukabumi—untuk membangun komitmen kolektif dalam menjaga lingkungan dan memitigasi risiko bencana. Karena sejatinya, mencegah satu bencana berarti menyelamatkan ribuan nyawa dan masa depan.