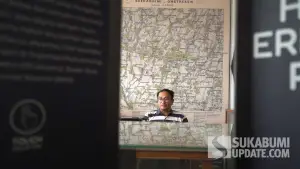SUKABUMIUPDATE.com - Menjelang 20 November, Hari Anak Sedunia, tahun 2025 ditutup dengan catatan kelam bagi perlindungan anak di Indonesia. Meskipun negara telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak dan memiliki kerangka hukum yang kokoh, suasana perayaan digantikan oleh kebisuan pilu. Realitas pahit menunjukkan bahwa ancaman terbesar bagi anak kini bukan berasal dari luar, melainkan dari lingkungan terdekat; rumah, gawai digital, dan orang-orang yang seharusnya dipercaya. Perlindungan yang secara hukum berdiri tegak kini runtuh akibat krisis moral dan kegagalan pengawasan di tingkat komunitas dan keluarga.
Data yang mengalir masuk ke meja Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sepanjang 2025 melukiskan pola yang mengerikan: mayoritas kekerasan tidak lagi bersifat acak, melainkan terencana dan sistematis, dengan pelaku yang memiliki akses mudah dan otoritas. Ini adalah ironi perlindungan yang paling menyakitkan. Bagaimana seorang anak bisa bersembunyi ketika predatornya adalah Ayah tiri, Paman yang akrab, atau bahkan Guru agama yang dihormati di pondok pesantren? Lingkungan yang dianggap suci dan aman rumah dan sekolahtelah bertransformasi menjadi titik nol trauma.
"Krisis yang kita hadapi adalah krisis kepercayaan pada lingkungan terdekat. Pelaku menggunakan kedekatan emosional dan kuasa mereka untuk menormalkan sentuhan yang tidak pantas. Ini bukan hanya masalah moral individu, tetapi masalah struktur sosial yang gagal mendidik orang dewasa tentang batasan dan privasi anak." Kata Dr. Seto Mulyadi, Psikolog Anak dan Pemerhati Perlindungan Anak Indonesia mengenai kepercayaan anak yang dieksploitasi, dan ketergantungan mereka pada figur otoritas yang digunakan sebagai senjata untuk memastikan kebisuan. Inilah mengapa kasus-kasus itu seringkali baru terungkap bertahun-tahun kemudian, setelah kerusakan mental korban terlanjur dalam.
Baca Juga: HJKS ke-155, Perumda BPR Jampangkulon Sukabumi Salurkan Sembako di Touring Ngabumi
 Menjelang akhir tahun, para pemerhati isu sosial mengatakan 20 November 2025 harus menjadi momen refleksi bukan perayaan. (Foto: IG/@sundabagja)
Menjelang akhir tahun, para pemerhati isu sosial mengatakan 20 November 2025 harus menjadi momen refleksi bukan perayaan. (Foto: IG/@sundabagja)
Kasus-Kasus yang Mengguncang Indonesia
Tahun 2025 diwarnai oleh serangkaian kasus yang seolah merobek selaput tipis perlindungan sosial. Kasus-kasus ini, yang mewakili ribuan kasus serupa yang tidak terlaporkan, menunjukkan betapa universalnya risiko kekerasan anak di Indonesia:
- Kasus "Santri Senyap" di Jawa Timur: Sebuah pondok pesantren (diberi nama samaran Al-Barakah) di Jawa Timur menjadi sorotan nasional setelah belasan santriwati berani melaporkan kekerasan seksual yang dilakukan oleh pemimpin atau ustaz mereka. Kekuatan otoritas keagamaan dan budaya tunduk pada guru menciptakan kondisi di mana kekerasan dapat berlangsung selama bertahun-tahun tanpa diketahui. Kasus ini menyoroti perlunya mekanisme pelaporan independen di lembaga pendidikan berbasis asrama.
- Tragedi "Kakak Tiri" di Kalimantan: Di sebuah kota kecil di Kalimantan, seorang anak perempuan berusia 10 tahun menjadi korban eksploitasi dan kekerasan yang dilakukan secara bergantian oleh kakak tiri dan ayah kandungnya sendiri selama lebih dari dua tahun. Kasus ini mengungkap kegagalan sistem pengawasan sosial di tingkat RT/RW dan kerentanan anak perempuan di lingkungan domestik yang rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan keluarga.
- Jaringan "Dunia Game" di Sumatera Utara: Kepolisian di Sumatera Utara berhasil membongkar sindikat grooming dan distribusi CSAM yang beroperasi melalui platform permainan daring (online gaming). Pelaku berhasil memanipulasi lebih dari dua puluh anak laki-laki dan perempuan dengan iming-iming hadiah game atau pengakuan. Kasus ini menegaskan bahwa ruang digital adalah arena eksploitasi baru, yang menuntut respon cepat dari penegak hukum yang berhadapan dengan pelaku anonim dan bukti yang mudah hilang.
Baca Juga: Fase Bulan Baru, Potensi Banjir Rob di Pesisir Sukabumi 19-25 November 2025
 "Paradoks terburuk dalam pengasuhan modern adalah ketakutan berlebihan kita terhadap orang asing fisik, sementara kita mengabaikan predator anonim yang beroperasi 24 jam sehari di ponsel anak-anak kita." - Sukabumiupdate (Sumber: pixabay/haniffer11)
"Paradoks terburuk dalam pengasuhan modern adalah ketakutan berlebihan kita terhadap orang asing fisik, sementara kita mengabaikan predator anonim yang beroperasi 24 jam sehari di ponsel anak-anak kita." - Sukabumiupdate (Sumber: pixabay/haniffer11)
Tahun 2025 juga menjadi saksi bisu pergeseran medan pertempuran. Jika dahulu anak-anak diburu di taman atau gang sepi, kini mereka diburu melalui layar 6 inci yang digenggam setiap hari. Predator siber memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk melakukan groomingpendekatan emosional yang manipulatifmelalui game online atau media sosial. Anak-anak yang kesepian atau mencari pengakuan di dunia maya menjadi sasaran empuk.
Anak-anak dipancing, diancam, dan diabadikan dalam bentuk CSAM (Child Sexual Abuse Material) yang kemudian beredar tak terkendali di jaringan gelap internet. Ancaman ini menjadi hantu tanpa wajah; pelakunya bisa berjarak ribuan kilometer, namun dampaknya langsung merusak psikis korban di kamar tidur mereka sendiri. Respons penegak hukum yang masih sering gagap terhadap bukti digital membuat kasus-kasus ini kerap terhenti, memberikan rasa impunitas bagi pelaku.
Henrietta Fore, Mantan Direktur Eksekutif UNICEF dalam laporan global mengenai keselamatan siber anak, mengtakan bahwa pandemi telah mempercepat 'migrasi' predator ke dunia maya.
“Alat grooming menjadi semakin canggih, dan tantangannya adalah bagaimana penegak hukum dapat beradaptasi dengan kecepatan yang sama. Kita tidak lagi berjuang melawan individu, tetapi melawan ekosistem eksploitasi global yang terorganisir," kata dia.
Baca Juga: Kaleidoskop 2025: Tren Kesehatan yang Paling Ramai Dibicarakan Tahun Ini
 "Gawai bukanlah musuh, tetapi kita belum mendidik anak dan orang tua tentang etika dan batasnya. Kita takut anak bertemu 'orang jahat' secara fisik, tetapi kita tidak mengajarkan mereka 'pintu mana yang harus ditutup' ketika berinteraksi dengan orang asing di media sosial."- Sukabumiupdate| Foto: Pexels.com
"Gawai bukanlah musuh, tetapi kita belum mendidik anak dan orang tua tentang etika dan batasnya. Kita takut anak bertemu 'orang jahat' secara fisik, tetapi kita tidak mengajarkan mereka 'pintu mana yang harus ditutup' ketika berinteraksi dengan orang asing di media sosial."- Sukabumiupdate| Foto: Pexels.com
Antara Palu dan Stigma
Ketika kasus akhirnya terungkap, perjalanan menuju keadilan bagi korban anak masih terjal dan menyakitkan. Hukum memang memegang palu, tetapi masyarakat memegang stigma. Proses peradilan yang berlarut-larut memaksa korban mengulang trauma mereka berulang kali di ruang penyidikan, di hadapan hakim, dan tatapan publik yang menghakimi. Sementara tuntutan jaksa sering kali tegas, putusan yang dijatuhkan di pengadilan terkadang terasa caping atau ringan jika dibandingkan dengan kehancuran masa depan yang dialami korbansebuah sinyal buruk bagi efek jera. Lebih dari itu, minimnya ketersediaan layanan rehabilitasi psikologis yang berkelanjutan dan terstandardisasi, terutama di daerah, berarti korban seringkali dibiarkan berjuang sendiri untuk pulih dari luka yang tak terlihat.
Janji perlindungan hukum terasa tumpul tanpa diikuti oleh jaring pengaman pemulihan yang kuat. "Masalah terbesar dalam sistem peradilan pidana anak kita adalah 'Viktimisasi Sekunder'. Korban diperlakukan seperti barang bukti. Kita perlu pelatihan masif bagi hakim dan jaksa agar mereka mengadopsi pendekatan berbasis trauma (trauma-informed approach), sehingga proses hukum tidak menjadi sumber trauma baru bagi anak." demikian, pernyataan yang disampaikan Prof. Dr. Sulistyowati Irianto, Pakar Hukum dan Gender Universitas Indonesia.
Membangun Benteng Baru
Menjelang akhir tahun, para pemerhati isu sosial mengatakan 20 November 2025 harus menjadi momen refleksi bukan perayaan. Solusinya tidak terletak pada penambahan undang-undang, melainkan pada aksi kolektif dan perubahan perspektif radikal. Pemerintah harus secara serius mengalokasikan anggaran untuk penguatan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) PPA hingga ke pelosok, bukan hanya di ibu kota. Keluarga harus didorong untuk mengadopsi pola asuh positif bebas kekerasan dan dilatih secara masif untuk literasi digital.
Baca Juga: Pendingin AC Itu Kuno! Tiongkok Malah Tenggelamkan Server ke Dasar Laut, Pengaruh Ibu Susi?
"Masyarakat yang benar-benar beradab diukur dari bagaimana masyarakat itu memperlakukan anak-anak yang paling rentan. Ketika kita gagal melindungi anak, kita tidak hanya kehilangan masa depan mereka, tetapi kita kehilangan kemampuan kolektif kita untuk berempati dan bertindak. Perlindungan anak adalah cerminan kesehatan moral sebuah bangsa," kata Dr. Hasto Wardoyo, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan pemerhati isu sosial.
Hanya dengan membangun kesadaran bahwa "diam adalah aib yang lebih besar" dan menjadikan setiap orang dewasa sebagai mata rantai pelindung, kita dapat berharap rumah, sekolah, dan ruang digital kembali menjadi benteng yang aman bagi generasi penerus. Jika tidak, Hari Anak Sedunia akan selamanya menjadi pengingat atas janji yang belum tertepati. Jelang 20 November 2025, refleksi pahit harus menjadi pengingat yang menyengat: undang-undang sekuat apa pun hanyalah tinta di atas kertas jika tidak dihidupkan oleh kesadaran dan keberanian kolektif. Kasus-kasus yang mengguncang sepanjang tahun ini, dari kamar pesantren hingga jejaring siber, adalah lonceng peringatan bahwa perlindungan anak adalah tanggung jawab yang tidak mengenal libur.
Kita tidak bisa lagi berlindung di balik norma-norma lama atau kepura-puraan bahwa kekerasan hanya terjadi di tempat jauh. Harapan untuk tahun 2026 harus diletakkan pada fondasi yang lebih jujur: membangun kembali benteng-benteng perlindungan keluarga, sekolah, dan sistem hukum dengan perspektif berbasis trauma dan tanpa kompromi. Hanya dengan begitu, Hari Anak Sedunia dapat benar-benar dirayakan sebagai perayaan hak, bukan sekadar peringatan akan kegagalan.