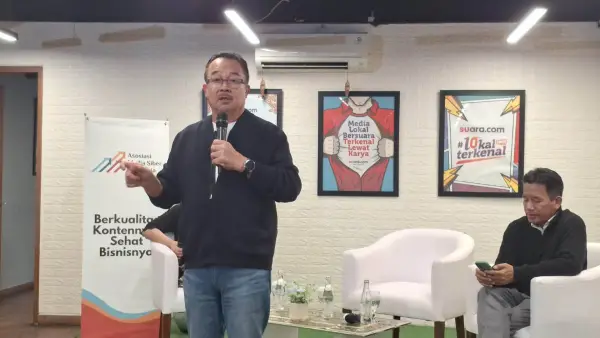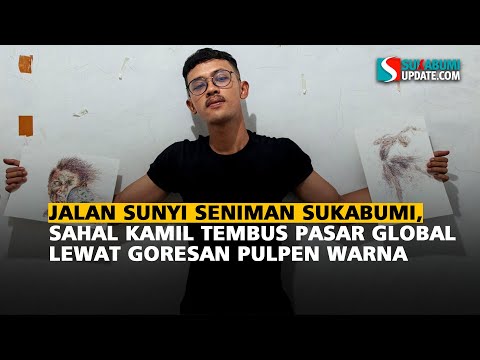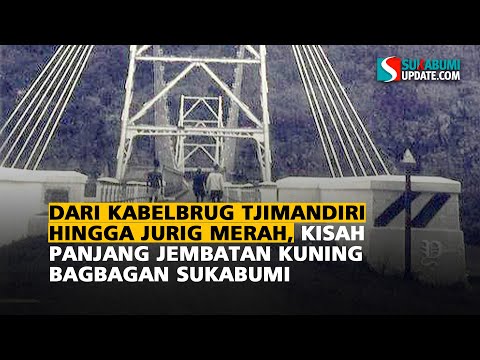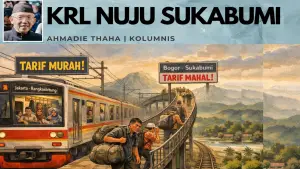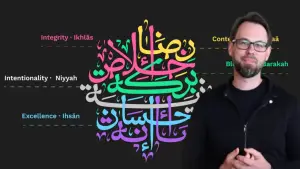Refleksi Pasca Suksesi KNPI Kabupaten Sukabumi 2025.
Oleh: CSA Teddy Lesmana, Dosen Prodi Ilmu Hukum Universitas Nusa Putra
"Di tangan pemuda, masa depan bukan ditunggu, tapi dipertaruhkan. Karena dalam setiap generasi, hanya yang berani membakar dirinya dengan nilai yang akan menjadi cahaya bagi yang lain."
Musyawarah Daerah (Musda) ke-XVI Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Sukabumi yang digelar di Yon Armed, Cikembang, pada 26 Mei 2025, menetapkan Yandra Utama Santosa sebagai Ketua DPD KNPI terpilih secara demokratis. Suksesi ini menjadi penanda penting di tengah stagnasi gerakan kepemudaan yang kerap terjebak dalam formalitas struktural dan defisit visi kolektif. Di tengah fragmentasi organisasi dan melemahnya semangat kebangsaan, terpilihnya Yandra membuka ruang harapan baru bagi pembaruan nilai-nilai organisasi pemuda.
Saya mengenal Yandra saat mengikuti International Conference yang diselenggarakan oleh Nusa Putra University di Jeddah, Arab Saudi, November 2024, yang diawali dengan pelaksanaan ibadah umrah. Dalam berbagai diskusi, saya melihat keseriusan intelektual dan keberpihakan moral dalam dirinya. Dalam satu sesi yang terekam dan saya unggah ke media sosial, ia mengutip Sutan Sjahrir: “Hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan.” Kutipan itu bukan sekadar retorika, tetapi penanda arah—sebuah pengingat bahwa organisasi pemuda bukanlah ruang formalitas, melainkan tempat menguji keberanian dan integritas.
Namun, euforia pemilihan tidak boleh membutakan kita dari krisis yang lebih dalam: apakah KNPI dan organisasi sejenisnya masih relevan di tengah generasi yang semakin individualistik, pragmatis, dan skeptis terhadap struktur formal? Laporan Badan Pusat Statistik (2023) menunjukkan bahwa hanya sekitar 30,5% pemuda Indonesia yang aktif dalam kegiatan organisasi kemasyarakatan. Laporan International IDEA (2023) memperkuat temuan ini: hanya 28% pemuda Indonesia terlibat dalam aktivitas politik atau sosial yang terorganisir. Sementara itu, riset PISA 2022 dari OECD menunjukkan penurunan signifikan dalam kemampuan literasi dan berpikir kritis di kalangan siswa Indonesia—sebuah gejala yang lebih luas dari krisis eksistensial kepemudaan.
Dari titik ini maka kita perlu mengevaluasi kembali raison d’être (alasan keberadaan yang mendasar) organisasi kepemudaan ini dalam konteks demokrasi, hukum, dan filsafat kenegaraan. Melalui refleksi ini, kita ingin peran KNPI sebagai wahana pembentukan karakter, kesadaran sipil, dan regenerasi kepemimpinan benar-benar dapat diwujudkan.
Pertanyaan mendasar yang kita ajukan adalah bukan hanya soal eksistensi organisasi, tetapi apakah ia masih mampu menjadi rumah nilai, bukan sekadar alat mobilisasi.
Organisasi Pemuda dalam Lintasan Hukum dan Demokrasi
Dalam dua dekade terakhir, dunia digital telah mengubah wajah keterlibatan. Generasi Z dan milenial hidup dalam arus informasi yang deras, dengan partisipasi yang lebih cair, cepat, dan visual. Aktivisme kini lebih sering lahir di ruang daring, dalam bentuk kampanye spontan dan petisi daring, ketimbang musyawarah dan pelatihan kader. Dalam lanskap seperti ini, KNPI tampak seperti kapal tua yang terapung di lautan algoritma.
Data BPS (2023) menunjukkan hanya 30,5% pemuda Indonesia aktif dalam organisasi. IDEA (2023) menyebutkan stagnasi partisipasi politik formal di bawah 30%. Bersamaan dengan itu, PISA (2022) mengonfirmasi melemahnya daya pikir kritis di kalangan pelajar. Maka tak heran bila generasi ini mahir membuat opini viral, tapi asing terhadap forum-forum deliberatif dan etika publik.
Padahal secara normatif, KNPI punya landasan konstitusional yang kuat. Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menjamin hak berserikat dan berkumpul. UU No. 40 Tahun 2009 menegaskan organisasi pemuda sebagai medium partisipasi aktif dan transformasi sosial. Dalam teori politik, Robert Putnam (2000) menyebut organisasi sukarela sebagai penopang social capital dan civic virtue; Jürgen Habermas (1996) menyebut ruang publik sebagai arena artikulasi kehendak rasional bersama. Namun apa jadinya jika ruang itu ditinggalkan generasi muda karena dianggap terlalu kaku dan eksklusif?
KNPI berada di titik krusial: bertahan sebagai simbol sejarah atau bertransformasi sebagai laboratorium kewargaan. Ia harus melepaskan beban nostalgia dan menyambut logika zaman. Bukan dengan mengejar sensasi digital, tapi dengan menyusun ulang narasi partisipasi: dari forum tatap muka ke ruang refleksi kolektif, dari kepengurusan ke kepemimpinan gagasan.
Raison d’Être Pemuda dalam Filsafat Kenegaraan
Soekarno pernah berkata, “Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia.” Ini bukan semboyan kosong. Dalam filsafat kenegaraan Indonesia, pemuda bukanlah pelengkap, melainkan pelopor. Mereka bukan hanya pewaris kemerdekaan, tetapi penentu arah kemanusiaan.
John Rawls (1971), dalam A Theory of Justice, memperkenalkan gagasan generational justice—kewajiban etis satu generasi untuk meninggalkan struktur masyarakat yang adil bagi generasi berikutnya. Paulo Freire (1970) menyebut pemuda bukan sebagai objek dalam pembangunan melalui pendidikan, tapi sebagai subjek transformatif yang harus dibangkitkan kesadarannya (conscientization). Disini kita bisa memaknai bahwa bagi Freire, organisasi yang tidak mampu mengelola imajinasi kreatif dan kesadaran untuk bangkit adalah bentuk kekerasan struktural.
Anthony Giddens (1991), dengan konsep reflexive modernity, menekankan bahwa institusi hanya bisa bertahan jika mampu mengevaluasi dirinya secara terus menerus. KNPI, dalam konteks ini, tak cukup hanya menjadi warisan sejarah; ia harus menjadi medan pembaruan.
Pemikiran kepemudaan di Indonesia pun memiliki akar kuat yang terus bergema. Sutan Sjahrir, misalnya, menegaskan bahwa pemuda harus menjadi manusia merdeka yang berpikir dan bertindak atas dasar kesadaran, bukan karena dorongan massa. Hatta, dalam gagasannya tentang demokrasi ekonomi dan kaderisasi bangsa, memandang pemuda sebagai agen perubahan yang harus berpijak pada nilai kejujuran dan tanggung jawab. Soedjatmoko menyuarakan bahwa masa depan Indonesia akan sangat ditentukan oleh kapasitas intelektual dan moral pemudanya dalam merespons perubahan zaman secara reflektif dan progresif.
Tokoh muda Indonesia era modern seperti Najwa Shihab misalnya, melalui ruang-ruang kritis yang ia bangun, menegaskan bahwa pemuda hari ini harus melek isu, peka terhadap ketidakadilan, dan berani bersuara. Sementara itu, Yudi Latif menulis bahwa pemuda Indonesia harus menjadi penjaga api kesadaran kebangsaan dan menjadi aktor perubahan etis yang bertanggung jawab secara historis dan moral. Dari pandangan-pandangan ini, jelas bahwa pemuda bukan sekadar pelengkap demokrasi, tetapi penentu kualitasnya. Pemuda adalah energi moral yang menuntut keberanian untuk berpikir merdeka. Dari sini kita tahu: pemuda bukan sekadar statistik demografi, tetapi subjek sejarah dan etika bangsa.
Raison d’Être pemuda dalam filsafat kenegaraan tidak sekadar berada pada garis struktural konstitusi, tetapi pada detak nilai yang memberi nyawa pada demokrasi itu sendiri. Di tangan pemuda, masa depan bukan ditunggu, tapi dipertaruhkan. Karena dalam setiap generasi, hanya yang berani membakar dirinya dengan nilai yang akan menjadi cahaya bagi yang lain. Maka pemuda bukan hanya pengisi jeda sejarah, tetapi obor yang menyalakan arah. Ketika organisasi kehilangan semangatnya, pemudalah yang seharusnya mengingatkan makna; ketika bangsa limbung oleh ilusi, pemudalah yang harus berdiri sebagai sumbu kesadaran.
Inilah sebabnya KNPI dan sejenisnya tidak cukup hanya bertahan—ia harus hidup. Hidup dalam makna, dalam nilai, dan dalam keberanian menjadi api bagi zaman yang kerap memadamkan makna. Dan dalam terang inilah, raison d’être pemuda menemukan bentuk tertingginya: menjadi pembaharu, bukan pewaris; menjadi penjaga nurani kolektif, bukan hanya pengikut prosedur; menjadi manusia yang menyalakan bangsa, bukan hanya menghitung tahun kemerdekaan.
Menyalakan Ulang Api Semangat Organisasi Pemuda
Revitalisasi KNPI menuntut lebih dari sekadar penggantian pengurus. Ia menuntut keberanian untuk melampaui formalisme, dan membangun ulang makna. Kaderisasi tak boleh berhenti pada pelatihan protokoler, tetapi harus menumbuhkan literasi etika, empati sosial, dan keberanian moral.
Platform digital bukan hanya alat promosi, tapi ruang diskursus: tempat pemuda mendebatkan masa depan bangsanya dengan keberanian dan kejujuran. Struktur organisasi harus bergeser dari vertikal ke horizontal, dari hierarki ke kolaborasi. Inisiatif seperti Youth Policy Hackathon, Sekolah Kebangsaan, dan Deliberative Youth Forum bukan hanya program, tapi model kepemudaan baru yang mencipta ruang dialog dan tanggung jawab bersama.
Namun yang lebih penting: KNPI harus menyalakan kembali api eksistensialnya. Di tengah dunia yang dipenuhi sinisme, organisasi ini harus menjadi terang nilai dan kehangatan solidaritas. Jika ia berhasil menyalakan nyala itu, maka generasi baru tidak hanya akan mewarisi nama KNPI—mereka akan memaknainya kembali.
Seperti kata Camus, “The only way to deal with an unfree world is to become so absolutely free that your very existence is an act of rebellion.” Maka keberanian pemuda untuk berpikir, menyala, dan bertindak bukan hanya bentuk partisipasi—tetapi bentuk keberanian moral.
Dan ketika pemimpin seperti Yandra Utama Santosa mampu berdiri bukan karena warisan, tetapi karena keberanian untuk memikul harapan kolektif, maka KNPI telah menemukan kembali raison d’être-nya: bukan sebagai kendaraan kekuasaan, tapi rumah nilai dan masa depan.
Semoga demikian adanya. Wallahu a’lam bish-shawab.