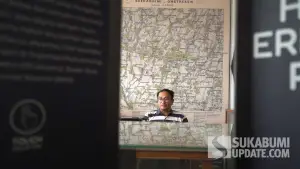SUKABUMIUPDATE.com - Pernahkah Anda membayangkan bisa jalan santai di hutan Amazon, mendaki Himalaya, atau menyelam di Great Barrier Reef tanpa meninggalkan ruang tamu? Teknologi Virtual Reality (VR) mutakhir membuat itu mungkin.
Dengan sekali pakai headset, kita bisa “healing instan” tanpa repot beli tiket, tanpa macet, bahkan tanpa takut digigit nyamuk. Saat ini, ada beberapa produk VR yang paling sering dibicarakan, berikut diantaranya dibawah ini:
Apple Vision Pro: harga Rp 55–75 juta.
Spesifikasi utama dengan layar micro-OLED dengan resolusi 4K per mata, chip ganda (M2 + R1), dan sistem kamera passthrough ultra-jernih. Kelebihan memberi pengalaman mixed reality paling mulus, seakan dunia nyata dan digital menyatu. Kekurangannya, selain harganya bikin kening berkerut, bobotnya lumayan, jadi tak cocok untuk dipakai lama-lama sambil rebahan.
Meta Quest 3: harga Rp 7–9 juta, versi ekonominya (Quest 3S) sekitar Rp 4,5–5,3 juta.
Spesifikasi utamanya dengan layar LCD dengan resolusi 2064×2208 per mata, prosesor Snapdragon XR2 Gen 2, dan dukungan passthrough berwarna. Kelebihannya ringan, tanpa kabel ribet, konten gamenya paling beragam. Cocok untuk pemula, keluarga, sampai pembelajaran interaktif. Kekurangannya, kualitas visual belum bisa menyaingi kelas sultan, dan baterainya agak cepat habis kalau dipakai intens.
Pimax Crystal Super: harga Rp 25 juta.
Spesifikasi utama dengan resolusi 2880×2880 per mata, lensa QLED + MiniLED, dan refresh rate 120Hz. Kelebihan memberikan pengalaman visual luar biasa tajam, cocok untuk simulasi balap dan penerbangan. Sensasi cockpit terasa nyata. Kekurangannya, ia butuh PC kelas monster, setidaknya kartu grafis RTX 4080 ke atas. Jadi investasi dobel: headset + PC.
Biofilia bilang kita butuh alam, VR bilang cukup headset. Jadi, siapa yang lebih ampuh menyembuhkan?
Teknologi ini memang keren, bahkan terasa seperti sihir modern. Tetapi, ada yang tidak bisa digantikan. Bau tanah basah setelah hujan, dinginnya embun pagi, atau suara jangkrik malam, semua itu belum ada versi VR-nya. Inilah paradoks manusia modern, punya perangkat canggih untuk merasakan alam digital, padahal taman kota di ujung jalan sering tak sempat kita kunjungi.
Fenomena ini sejatinya sudah diteorikan dalam hipotesis biofilia yang dikemukakan Edward O. Wilson dalam bukunya Biophilia (1984). Wilson menyebut bahwa manusia secara alami memiliki keterikatan dengan alam.
Riset modern mendukungnya, studi University of Exeter (2019) menemukan bahwa orang yang menghabiskan dua jam seminggu di alam terbuka cenderung lebih sehat dan bahagia. Jepang bahkan mempopulerkan praktik shinrin-yoku atau forest bathing dan hasilnya, kadar stres menurun drastis setelah berjalan di hutan. Namun, hidup kita justru kian jauh dari alam. Rata-rata orang Indonesia menghabiskan lebih dari 5 jam per hari di depan layar ponsel (Screen Time Report, 2023).
Bandingkan dengan waktu berinteraksi dengan ruang hijau, yang kalau dihitung-hitung sering hanya menit. Akibatnya, biofilia kita kian terpinggirkan oleh notifikasi, deadline, dan scroll tanpa ujung.
Meski begitu, teknologi tidak selalu menjadi musuh. Banyak inovasi yang justru membantu kita menjaga relasi dengan alam. Mulai dari aplikasi penghitung jejak karbon, drone penanam pohon, hingga sensor kualitas udara di kota-kota besar. Bahkan, ada program menanam pohon virtual yang benar-benar diwujudkan di lapangan. Jadi, teknologi bisa menjadi jembatan, bukan tembok.
Tetapi, kita tetap harus jujur, segelas kopi di teras rumah sambil menatap sawah, atau misalnya obrolan sederhana di warung nasi Mang Maman bersama sahabat lama, memberi efek yang lebih nyata daripada piknik digital. VR bisa membantu kita membayangkan, tapi hanya alam asli yang bisa menyembuhkan.
Pada akhirnya, biofilia bukan soal gadget yang kita pakai, melainkan pilihan, maukah kita meluangkan waktu untuk menyentuh tanah, mencium udara segar, dan menatap langit senja? Healing terbaik tidak perlu di-download, karena ia selalu ada di luar pintu rumah kita.
Penulis: Danang Hamid