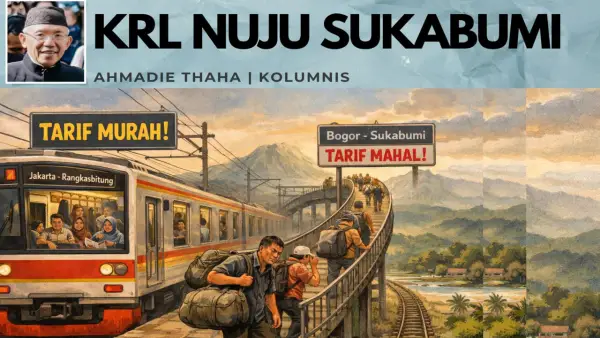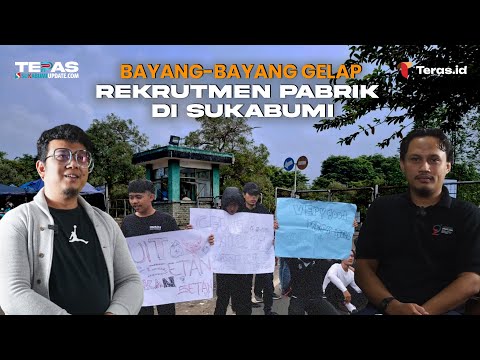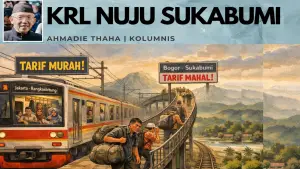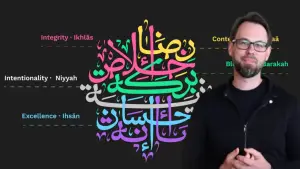SUKABUMIUPDATE.com - Stigma ‘Pemalas’ yang sering kali disematkan kepada Suku Sunda bahkan diperbandingkan dengan suku lainnya yang dianggap rajin tak jarang kita jumpai atau bahkan jadi pengalaman pribadi. Namun demikian, pertanyaan muncul, apakah sifat pemalas itu sejatinya dimiliki orang sunda atau hanya stigma yang sengaja disematkan?. Mari kita bedah berdasarkan perspektif sejarah.
Irman Firmansyah selaku pegiat sejarah di Sukabumi sekaligus penulis buku Soekaboemi The Untold Story mengatakan, penyematan kata pemalas bagi orang sunda muncul pada masa kolonial yang diduga sengaja disematkan oleh Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) kepada orang pribumi dan berkembang hingga saat ini.
“Pada masa kolonial tidak hanya orang sunda yang dianggap pemalas, bahkan orang Jawa pun dianggap pemalas oleh VOC yang berkuasa saat itu. Mereka dianggap pemalas karena tidak bekerja sesuai prosedur dengan target orang Eropa,” ujar Irman kepada sukabumiupdayte.com.
Baca Juga: Kabel Listrik Dicuri, Warga Dua RW di Cibadak Sukabumi Gelap Gulita
Menurutnya, stigma pemalas bagi orang sunda juga sengaja dibentuk sebagai pembenaran terhadap perlawanan diam diam yang dilakukan orang sunda. Saat melakukan eksploitasi di wilayah Priangan, VOC tidak mampu mengatur masyarakat sunda sendiri karena keterbatasan personil maupun biaya.
“Pada akhirnya mereka memerintah dengan sistem tidak langsung yang disebut Indirect Rules, yaitu dengan menggunakan para Bupati atau pemimpin wilayah lokal untuk membantu kepentingan VOC. Sistem ini tetap dilakukan hingga masa Hindia Belanda karena dianggap masih efektif,” kata dia.
Di sisi lain, kebijakan VOC yang melakukan eksploitasi alam di wilayah sunda dengan konsep Preanger Stelsel menjadi masalah bagi masyarakat sunda karena tidak sesuai dengan nilai-nilai kasundaan. Preanger stelsel maupun cultuur stelsel (Tanam Paksa) sebagai kebijakan sesudahnya, memaksa masyarakat sunda dengan prosedur pekerjaan kolonial yang ketat dan berorientasi pada target. Masyarakat dipaksa menanam komoditi tertentu yang dibayar dengan murah dan target yang harus terpenuhi.
“Masyarakat sunda yang merupakan masyarakat ekologis dan berdampingan dengan alam, tidak mengenal eksploitasi berlebihan karena mengejar target. Hidup masyarakat sunda bersandar pada keseimbangan alam dan memanfaatkan alam seperlunya sesuai kebutuhan, bukan untuk keserakahan,” ucapnya.
Baca Juga: Tiga Wajah Sukabumi: Hutan, Pengetahuan, dan Ekonomi yang Tumbuh dari Tanah Sendiri
“Contohnya di Sukabumi terdapat wilayah Kabuyutan yang dituangkan dalam prasasti Sanghyang tapak yang melarang orang untuk mengambil ikan dan sumber dayanya dengan ancaman yang mengerikan,” tambahnya.
Selain itu, masyarakat sunda mengenal konsep Patanjala yang melestarikan sumber-sumber alam mulai dari gunung, hutan, sungai hingga ke laut. Maka tidak heran jika dalam masyarakat sunda terdapat klasifikasi hutan yaitu hutan larangan, hutan tutupan dan hutan baladahan. Masyarakat bebas menggunakan sumber daya hutan di hutan baladahan.
Klasifikasi ini kemudian dihancurkan oleh sistem kolonial yang memanfaatkan hutan sebagai lahan perkebunan modern. Oleh sebab itu, ketika hutan dibuka sebagai perkebunan maka pola waktu kerja masyarakat sunda juga berubah, dari yang menggunakan waktu dzuhur sebagai tanda berhenti bekerja dan magrib untuk mulai menutup rumah, kemudian berubah menggunakan jam.
Sistem Jam kerja eropa pada masa VOC dapat mencapai 12-16 jam per hari dan 6-7 hari kerja dalam satu minggu. Kalender sunda yang diantaranya mengatur hari baik, hari bertani, waktu menebang pohon dan lain lain digantikan oleh kalender masehi yang tak memiliki makna spiritual dan hanya menekankan fungsi profan.
“Bagi masyarakat sunda hal itu merupakan perbudakan karena masyarakat sunda mengacu pada keseimbangan antara bekerja, beristirahat dan berkumpul dengan keluarga. Hal ini bukanlah hal yang keliru karena pada masa modern dikenal dengan istilah smart work dan work balancing. Namun zaman pada masa itu justru belum dikenal oleh orang Eropa,” tuturnya.
Baca Juga: Joey Pelupessy Dikabarkan akan Menyusul Thom Haye untuk Berseragam Persib Bandung
Perubahan kalender juga menyebabkan pola ritual masyarakat sunda berubah. Padahal masyarakat sunda merupakan masyarakat religius yang selalu berhubungan dengan karuhun dan norma norma berkelanjutan.
“Namun, sifat masyarakat sunda sendiri menghindari konflik. Jika tidak setuju masyarakat sunda tidak pernah membanting pintu, tapi menutupnya pelan-pelan kemudian pergi dan tak kembali. Hal ini juga terjadi di Sukabumi ketika masa era Tanam Paksa. Para peladang (ladang disebut juga huma atau tipar) di wilayah utara Sukabumi yang banyak dihuni administrasi Belanda, berbondong-bondong pindah ke selatan meninggalkan ladangnya,” tandasnya.
Dalam konteks ini julukan pemalas dari orang-orang Belanda lebih sebagai stigma yang dibentuk pada orang yang tidak mau dieksploitasi berdasarkan sistem kolonial. Bagi masyarakat sunda sendiri semacam revolusi sunyi, perlawanan tanpa kerusakan dengan menghindari eksploitasi berlebihan sehingga Belanda tidak bisa memanfaatkannya. Namun stigma ini juga diperparah dengan munculnya tokoh Kabayan dalam cerita lisan masyarakat, yang diasosiasikan dengan orang sunda yang malas dan selalu bercanda.