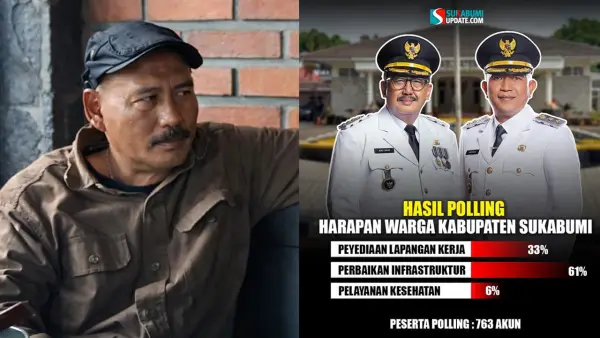Oleh: Hamidah,M.Pd
Praktisi Pendidikan
Perdebatan tentang poligami sering kali berhenti pada satu titik buntu: seolah kritik terhadap praktik poligami sama dengan penolakan terhadap hukum agama. Padahal, keduanya bukanlah hal yang identik. Poligami sebagai ketentuan agama tidak pernah berdiri sebagai izin bebas, melainkan sebagai hukum bersyarat yang sangat berat dan di situlah persoalan bermula.
Masalahnya bukan pada poligami itu sendiri, tetapi pada manusia yang menjalankannya tanpa memenuhi syarat moral dan keadilan yang menjadi ruh utama hukum tersebut.
Dalam Al-Qur’an, izin poligami hadir dalam konteks perlindungan terhadap perempuan dan anak yatim, sekaligus disertai peringatan keras tentang keadilan. Bahkan, ayat yang sama menutup dengan penegasan bahwa jika takut tidak adil, maka satu saja. Ini bukan sekadar opsi, tetapi arah hukum. Poligami bukan promosi, melainkan pembatasan atas praktik liar pra-Islam yang menempatkan perempuan sebagai objek.
Baca Juga: Profil Belajar Siswa (PBS) sebagai Instrumen Strategis Pendataan PDBK di Madrasah
Namun dalam praktik kontemporer, arah hukum ini sering dibalik. Yang seharusnya menjadi rem, justru dijadikan pedal gas. Keadilan direduksi menjadi kemampuan finansial semata, seolah nafkah cukup untuk menebus luka batin, kecemasan psikologis, dan ketimpangan relasi kuasa. Padahal adil dalam Islam mencakup waktu, perhatian, perlakuan, dan martabat hal-hal yang secara manusiawi sangat sulit, bahkan nyaris mustahil, untuk diseimbangkan.
Di sinilah ironi besar itu muncul: yang dibela adalah hukumnya, tetapi yang diabaikan adalah nilai keadilannya.
Dalam konteks Indonesia, praktik poligami tidak cukup hanya berlindung di balik dalil agama. KUHP terbaru secara tegas memberi ruang pemidanaan terhadap praktik perkawinan yang melanggar ketentuan hukum, termasuk poligami tanpa izin resmi dan tanpa prosedur yang sah. Negara melihat dampak sosialnya: perempuan yang dirugikan, anak yang terabaikan, dan relasi keluarga yang timpang.
Ini menegaskan satu hal penting: agama dan hukum negara sama-sama menempatkan keadilan sebagai syarat mutlak, bukan formalitas.
Dalih yang sering diulang “daripada zina, lebih baik poligami” juga menyimpan kekeliruan logika yang serius. Ia menyederhanakan pilihan moral manusia seolah hanya ada dua pintu: zina atau poligami. Padahal masih ada pintu ketiga yang justru paling utama: menahan diri, setia, dan bertanggung jawab. Tidak semua hasrat harus dilegalkan, dan tidak semua keinginan berhak dibungkus dengan simbol kesalehan.eadilan, tanpa persetujuan yang jujur, tanpa tanggung jawab emosional dan sosial, maka yang lahir bukan ibadah—melainkan kedzaliman yang dilegalkan secara sepihak. Dan kedzaliman, dalam bentuk apa pun, tidak pernah dibenarkan oleh agama.
Maka kritik terhadap praktik poligami yang timpang bukanlah serangan terhadap Islam, melainkan upaya mengembalikan Islam pada nilai etikanya. Sebab hukum agama tidak turun untuk memuaskan ego, tetapi untuk menjaga martabat manusia.
Jika hari ini banyak pelaku poligami tersandung hukum negara, sesungguhnya itu bukan kriminalisasi agama, melainkan konsekuensi dari kegagalan manusia memenuhi syarat keadilan yang ditetapkan agama itu sendiri.
Dan di titik inilah kita perlu jujur bertanya:
Apakah yang sedang kita bela adalah syariat,
atau sekadar keinginan yang dibungkus dalil?